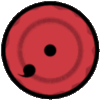Posted by : Dewi Otaku
Sabtu, 21 Januari 2012
Prolog
Fajar kembali datang menyapaku hari ini. Gelap malam mulai menerang, digantikan oleh berkas sinar mentari merah yang samar. Lampu-lampu jalan masih menyala, dan tidak ada seorang pun yang berada di jalanan. Mereka pada umumnya memang masih berada di dalam rumah jam-jam segini, tidur atau bersiap-siap menyambut hari.
Dari sisi jendela kamarku yang terletak di lantai dua, aku memandang tepat ke arah langit dini hari. Sudah menjadi kebiasaanku untuk menerawang ke luar jendela pada saat fajar menyingsing, dan itu pulalah yang kulakukan kali ini. Awan-awan gelap yang disinari cahaya kemerahan atau rumah-rumah yang lampunya masih menyala menjadi pemandangan yang jamak kulihat, tapi bukan itu yang kutunggu-tunggu.
Tak lama berselang, sebuah skuter yang melintas dari jalan utama berhasil menarik perhatianku. Ya, skuter itu—skuter yang selalu melewati jalan di bawah sana setiap menjelang pagi—merupakan sesuatu yang sedari tadi kunantikan. Baiklah, aku memang tidak menantikan skuter itu, aku menantikan pengendaranya. Dia adalah seorang cowok kurus yang senantiasa menyematkan sebilah papan seluncur di badan samping skuternya itu. Mataku terus mengikuti cowok itu (dan skuternya, tentu saja) hingga ia berhenti tepat di depan sebuah halte bus. Ia lantas turun dari skuternya, menaruh helmnya di spion, dan lalu membeli sekaleng minuman dari mesin penjual otomatis yang ada di sana sebelum akhirnya duduk di bangku halte. Beberapa saat kemudian, dua orang cowok lain lantas datang menghampiri cowok tersebut dengan sepasang skuter pula. Aku memperhatikan saat cowokok itu bercanda dengan teman-temannya, dan setelah ketiganya berlalu dengan skuter mereka, aku kemudian menutup jendela kamarku dengan tirai beralumunium. Kumatikan lampu, lalu kuseret langkahku menuju tempat tidur.
Di bawah balutan selimut, aku mengingat bayangan cowok itu sejenak. Selama bertahun-tahun, aku selalu melihatnya di tempat yang sama, halte bus itu. Selama bertahun-tahun aku selalu melihat cowok itu di waktu yang sama, menjelang fajar. Merupakan suatu hal yang wajar kalau lama-kelamaan aku mulai tertarik padanya, kan? Rasanya, sda sesuatu yang khusus pada dirinya, sesuatu yang menjadi semacam magnet bagiku. Inikah yang orang-orang sebut dengan “cinta”, saat di mana kamu melihat seseorang meskipun orang tersebut tidak hadir di hadapanmu? Aku terus memikirkan sosok cowok itu selama beberapa saat hingga akhirnya kuputuskan untuk memejamkan mata dan membiarkan diriku terbawa ke alam mimpi.
***
1
Aku, Gadis yang Hidup dalam Gelap
Perlahan tapi pasti, matahari mulai muncul dari kaki langit. Burung-burung yang terbang mencari makan menandakan bahwa kehidupan di Kamakura—sebuah kota kecil di pinggir laut—sudah dimulai. Kereta api berwarna hijau dengan garis putih kecoklatan melintasi jalan, membawa orang-orang pergi ke tempat kerja dan sekolah. Beberapa penduduk lokal yang memang sudah terbiasa berseluncur di pagi hari mengeluarkan papan seluncur mereka untuk beratraksi di atas ombak, sementara sebagian besar lainnya memenuhi jalan-jalan sempit kota. Begitulah keadaannya di kota ini; dari matahari terbit hingga terbenam kembali, semuanya sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Tiada yang berubah.
Tanpa terasa, satu hari telah berlalu, dan matahari—sekali lagi—kembali tenggelam di barat. Aku membuka mata beberapa saat setelah jam wekerku mulai mengeluarkan suara deringnya, membuat kamarku yang senyap menjadi bising. Tanganku meraih-raih jam bulat berwarna kuning itu, dan dengan segera, kupencet tombolnya untuk mengakhiri suara dering yang telah membuatku terjaga. Jendela kamar lantas kubuka lebar-lebar. Setelah menghirup udara malam yang dingin dan sejuk sebanyak mungkin, aku lalu menggeliat perlahan. Kubiarkan angin malam yang berhembus lewat jendela mengibarkan rambut hitam panjangku.
Tak lama setelah itu, aku sudah berganti baju, dari kaos biruku yang kugunakan tidur seharian menjadi sweter abu-abu. Aku lantas mengambil kotak gitarku dan berlari turun ke bawah—ke ruang keluarga. Kudapati Otousan dan Okaasan berada di sana. Otousan tengah mengguntingi kuku jari-jari kakinya, sementara Okaasan tengah menyiapkan makan malam.
“Itu dia, Kaoru ada di sini,” ujar Otousan saat melihatku menaruh kotak gitarku di samping pintu geser. Perlahan, aku lantas memasuki ruang keluarga dan mengambil krim tabir surya dari atas lemari dan lantas mulai melumurkannya di tangan dan wajahku. Menyadari aku tengah melakukan hal itu, Okaasan beralih dari kesibukannya menata meja.
“Malam ini kamu pergi juga?” tanya Okaasan kepadaku, yang kujawab dengan anggukan.
“Setiap malam membuat lagu terus,” Otousan menimpali tanpa memandangku (dan ia terus melihat ke arah jempolnya!), “itu yang kaulakukan, kan?”
Aku bergumam perlahan menanggapi pertanyaan Otousan. Yah, siapa pun tahu kalau itu berarti sama dengan “ya.”
“Apa itu ada maknanya?” tanya Otousan lagi kepadaku.
“Apa ada yang salah dengan itu?” aku membalas pertanyaan Otousan.
Setelah selesai dengan acara gunting kukunya, Otousan lalu bangkit dari kursi. “Apa boleh buat. Karena hari ini aku libur,” ia berkata kepada Okaasan, “aku akan pergi melihatnya tampil.”
“Akan kubunuh kalau datang,” aku berkata cepat-cepat sambil terus melulurkan tabir surya di lenganku.
Otousan tampak sedikit terkejut mendengar kata-kataku, tapi dia akhirnya mengerti. Sepertinya, dia tahu kalau putrinya tidak ingin dilihat. “Ya sudah kalau begitu.”
Aku kemudian menggosok-gosokkan kedua tanganku, memastikan kalau tabir surya yang kukenakan sudah sepenuhnya terserap ke dalam kulit. “Kau tahu kapan matahari akan terbit, kan?”
Okaasan lantas bertanya kepadaku, yang—sekali lagi—kubalas dengan gumaman. “Jangan cuma menjawab dengan ‘hem’ saja,” tegurnya.
“Jam 4.40 pagi,” kataku. Sesuai permintaannya, aku menjawab dengan kata-kata.
“Kalau begitu, pastikan kamu sudah ada di rumah sebelum jam empat,” tambah Okaasan lagi.
Sementara Okaasan meletakkan semangkuk besar sup, aku beranjak ke tempat duduk. “Aku mengerti,” jawabku perlahan.
“Juga jangan pergi terlalu jauh,” Okaasan kembali menasihati.
Aku, yang kini tengah memegangi gelas selagi Otousan menuangkan air ke dalamnya, hanya menjawab dengan jawaban standar, “Iya, iya.”
Setelah itu, Otousan memulai makan malam bersama dengan ucapan itadakimasu (semacam ucapan selamat makan), dan aku lantas mulai menyantap makanan yang ada di depanku.
***
Saat-saat setelah makan malam merupakan saat yang menyenangkan bagiku. Pada saat itu, aku akan keluar rumah, dan—seperti kata Otousan—membuat lagu. Tapi, sebenarnya aku lebih sering menyanyikan lagu yang kubuat itu ketimbang membuat lagu baru. Seperti saat ini. Setelah makan malam, aku membawa kotak gitarku keluar melewati gerbang rumah bersamaku. Aku menunggu sejenak saat palang pengaman kereta api menutup, dan setelah palang itu kembali membuka, aku melanjutkan perjalananku melewati sebuah gang perumahan dan pertokoan yang sepi bernama Yamacho-ri. Kemudian, aku melangkahkan kakiku menuju tempat biasanya aku bermain—depan stasiun. Di tempat ini, biasanya aku akan duduk di lantai dan mulai membuka kotak gitarku untuk kemudian memainkannya. Beberapa batang puntung rokok yang mengotori lantai kusapu dengan menggunakan sepatuku. Lantai ini akan kupakai, jadi wajar saja kalau aku meminggirkan puntung-puntung rokok itu. Ketika aku tengah membersihkan lantai yang akan kugunakan dari puntung rokok dan sampah, aku melihat sepasang polisi mendekati tempatku berada dengan mobil patroli mereka. Memang bukan merupakan hal yang wajar jika seorang gadis seusiaku terlihat berada di luar rumah jam-jam segini.
“Apa dia tersesat?” samar-samar, aku mendengar polisi yang lebih muda bertanya kepada polisi senior di sampingnya.
“Tak apa, kamu tak perlu mencemaskan gadis itu,” jawab sang polisi senior. “Orang tuanya sudah memberitahukan sebelumnya.”
“Memberitahukan apa?”
“Bagaimana mengatakannya, ya...,” polisi senior itu menahan kalimatnya, mencari penjelasan yang paling mudah, “XP adalah sejenis alergi. Kalau terkena matahari, maka penderitanya bisa mati.”
“Hah?” polisi yang lebih muda terkejut. Tidak heran. Ada berapa banyak alergi di dunia ini yang dapat membuatmu meninggal hanya karena terkena sinar matahari?
“Itulah sebabnya ia hanya dapat keluar di malam hari.”
Aku tersenyum mendengar percakapan mereka, tapi aku tidak memedulikannya. Alih-alih begitu, aku tetap membersihkan puntung-puntung rokok atau sampah lain yang mengotori lantai. Setelah merasa kalau lantai itu sudah cukup bersih, aku kemudian duduk di situ dan membuka kotak gitarku. Kunyalakan sebatang lilin yang sengaja kubawa dari rumah, sekadar untuk menemaniku bermain gitar. Setelah itu, aku menyetem gitarku, menggenjrengnya sekali, dan kemudian mulai menyanyikan lagu ciptaanku.
♪ Dare no tame ni ikite iru no?
Saenai hibi wo sugoshite, yeah
Yoasa mo itami mo
Dono kurai, kanjiteru no?
Tarinai kinou ni obore
Yume ni kaita kyou
Soraenakutemo, yeah, yeah
Yoake mae no matataku hoshi wa
Kiete itta no?
Asu e itta no?
Tomorrow never knows..., It’s happy line!
(Demi siapakah aku hidup?
Hari-hari berawan telah berlalu
Rasa lemah ini, rasa sakit ini
Seberapa banyak yang kau rasakan?
Aku menenggelamkan diriku dalam hari kemarin dengan sia-sia
Kutulis mimpiku hari ini
Meskipun itu belum selesai, yeah, yeah
Bintang-bintang yang berkelap-kelip sebelum fajar
Apakah mereka benar-benar hilang?
Atau mereka akan kembali lagi besok?
Hari esok tiada yang tahu... Ini adalah ucapan bahagia!) ♪
***
Namaku Amane Kaoru. Enam belas tahun. Selama ini, semenjak lahir, aku hanya bisa keluar malam dan tidak bisa keluar saat siang ketika matahari bersinar. Aku menderita sebuah penyakit kulit bernama Xeroderma Pigmentosum atau biasa disingkat XP. Kulitku sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet yang berada dalam sinar matahari. Apabila terekspos sedikit saja, maka akan timbul bercak-bercak coklat yang berisiko tinggi untuk berkembang menjadi kanker. Lebih-lebih jika aku seharian berada di luar, bisa dibayangkan bagaimana dampaknya, kan?
Meskipun aku tidak bisa beraktivitas di siang hari, setidaknya aku masih punya sesuatu untuk dilakukan pada malam hari. Ya, jika malam sudah tiba, aku akan keluar membawa gitarku dan mulai bernyanyi di sini—di depan stasiun—sendirian. Aku suka mengarang-ngarang lagu dan, tentu saja, memainkannya dengan gitarku. Cita-citaku yang paling utama adalah masuk dapur rekaman dan merilis album yang berisikan lagu ciptaanku sendiri; meskipun sepertinya itu mustahil, ya? Aku telah menjalani kehidupan seperti ini selama bertahun-tahun, dan kurasa, aku cukup menikmatinya. Namun, hari esok memang tak bisa ditebak. Siapa yang tahu kalau keesokan harinya, hidupku akan mulai berubah?
***
2
Misaki dan Pertemuan Pertamaku dengan Cowok Itu
Dalam gelapnya dini hari, aku berjalan melintasi jembatan menuju rumahku. Aku sudah harus berada di rumah sebelum terbit matahari, ingat? Kemudian, aku melewatinya; halte bus yang biasa dipakai cowok berskuter dan berpapan seluncur untuk menunggu kedua temannya. Kakiku lantas kuarahkan menuju ke halte itu. Kutaruh kotak gitarku di samping bangku halte, lalu duduk di sana. Tanpa kusadari, tanganku mulai mengelus-elus bangku yang berwarna biru itu. Di sinilah ia biasa duduk, cowok itu. Kupandangi bangku itu sejenak, dan tanpa berpikir panjang, kurebahkan diriku di atas bangku. Terasa sejuk dan nyaman. Ketika tengah tidur-tiduran itu, sekonyong-konyong mataku melihat papan penanda bus untuk berhenti Papan itu! Papan yang selalu membuat pandanganku dari jendela kamar ke bangku halte terhalang. Aku bangkit dari bangku, dan tak lama setelahnya, menggeser penanda itu beberapa meter ke kiri. Beres! Mulai sekarang, aku bisa melihatnya dengan lebih leluasa.
Ketika tengah menyapukan pandanganku ke sekitar (sambil setengah berharap cowok itu akan segera datang), aku tiba-tiba saja mendengar alarm jam tanganku berbunyi. Ah, itu dia. Isyarat bahwa fajar sudah akan tiba, sekaligus petunjuk untukku agar segera pulang. Aku mengecek jam tanganku untuk memastikan sudah jam berapa sekarang. Jam empat, ya....sebaiknya aku segera kembali ke rumah kalau tidak mau terpapar sinar matahari.
***
Pagi ini, di balik tirai beralumunium yang berfungsi mencegah sinar UV, aku kembali duduk-duduk di samping jendela. Seperti biasa, aku mendapati cowok itu sudah berada di depan halte bus dengan skuter dan papan selancarnya. Kali ini, aku dapat mengamatinya dengan lebih bebas karena tidak ada lagi papan yang menghalangiku. Kuperhatikan ia menunduk seperti tengah memainkan sesuatu (mungkin tangannya), dan ketika sadar kalau papan penanda bus yang biasa telah berpindah sekitar lima meter dari posisi normal, ia bergegas menghampiri papan itu sembari celingukan. Aku tertawa tertahan melihat cowok itu bingung sendiri. Setelah aku melihatnya berlalu dengan kedua temannya tak berapa lama kemudian, aku lantas menutup jendela dan beranjak ke tempat tidur. Samar-samar, kudengar suara gaduh di lantai satu. Otousan adalah pemilik sebuah restoran kecil pinggir pantai, jadi dia pastilah tengah mempersiapkan berbagai hal bersama Okaasan untuk membuka restorannya itu. Namun, aku sudah terbiasa dengan kegaduhan itu, jadi aku tidak peduli dan memilih untuk bersiap-siap tidur.
Hari ini, Misaki memberitahuku kalau ia akan mampir. Ia adalah sepupuku sekaligus sahabatku selama ini, tapi karena penyakitku ini, aku tidak bisa bersama-sama dengannya ke sekolah. Dia cewek yang baik bagiku, tapi mungkin tidak bagi guru di sekolahnya. Bayangkan, ia sering membolos hanya untuk menemaniku! Seperti saat ini, ia datang ke rumah pada saat ia seharusnya berada di sekolah.
“Hei, hei, hei,” Otousan menghalangi dengan kakinya saat Misaki—masih dengan seragam sekolah—sudah berada di serambi.
“Osh!” jawab Misaki. Itu merupakan kata-kata favoritnya untuk menanggapi sesuatu.
“Jangan bilang ‘Osh’ ke aku,” jawab Otousan, “kamu bolos lagi, kan?”
“Osh! Kaoru mana?”
“Dia sedang tidur,” Otousan kembali menjawab dengan kaki kanannya masih terangkat, “kalau kamu membangunkannya sekarang, dia akan membunuhmu.”
“Kalau aku yang membangunkannya, tidak akan apa-apa,” balas Misaki.
Mendengar Misaki berkata seperti itu, Otousan lantas menurunkan kakinya, membuat cewek berkaca mata merah itu dapat lewat. “Kalau begitu, ya sana,” tambahnya. Ia lantas keluar rumah, sementara Misaki beringsut ke dalam.
“Obasan, ada yang baru lagi?” ujar Misaki ketika ia mendapati sesuatu tergantung di sisi lemari. Sebuah pakaian khusus berwarna abu-abu yang dapat menghalangi sinar UV. Aku harus mengenakan pakaian itu apabila hendak keluar rumah di siang hari, dan rasanya, ehm, tidak terlalu nyaman. Jujur saja, dengan tudung kepala khusus yang dilengkapi plastik untuk menerawang keluar, aku merasa seperti peneliti di reaktor nuklir jika mengenakan pakaian itu.
“Yang lama sudah kekecilan buat dia,” jawab Okaasan.
“Yah, tentu saja...,” gumam Misaki sambil meraih ujung pakaian itu.
“Kurasa sebaiknya jangan disentuh,” kata Okaasan tiba-tiba. Ia sudah membawa dua buah keranjang yang berisikan perlengkapan retoran. Kemudian, sambil mengenakan sepatu, Okaasan melanjutkan, “Kaoru akan mengetahuinya. Oh, Misaki-chan,” ia berbalik ke arah Misaki yang kini sudah melepaskan pakaian khususku, “aku tidak ingin mengatakan ini, tapi jangan habiskan barang yang ada di kulkas, ya.”
“Baik,” seru Misaki, yang sekaligus mengiringi kepergian Okaasan ke restoran. Setelah itu, dengan setengah berlari, ia menaiki tangga dan bergegas menuju kamarku.
Kalau tadi Otousan bilang ke Misaki kalau aku sedang tidur, maka ia sebenarnya salah. Aku sudah bangun sejak setengah jam lalu, dan wajahku merengut saat melihat seorang supir bus dengan bersusah payah mengembalikan papan penanda bus yang semalam kupindahkan. Misaki menerobos masuk ke kamarku saat aku masih memandang ke luar, dan ia dengan tergopoh-gopoh menghampiriku sambil bertanya apa yang kulihat.
“Bukan, bukan apa-apa,” jawabku. Namun, Misaki tampak tidak percaya begitu saja; ia tetap menyapukan pandangannya ke luar. Aku lantas beranjak dari sisi jendela, sementara Misaki masih melongok-longok, berusaha mencari tahu apa yang sedari tadi kuperhatikan.
***
Malam kembali datang menemuiku, dan di atas sana, bulan keperakan terlihat menggantung. Seperti biasa, aku akan pergi keluar saat malam tiba untuk memainkan gitarku di depan stasiun. Namun, kali ini aku tidak sendirian karena ada Misaki bersamaku. Kami bersepeda bersama menuju depan stasiun lewat Yamacho-ri yang selalu kulalui tiap malam. Misaki yang duduk di depan, dan dia mengendarai sepedaku seperti orang mabuk. Lihat saja, ia terus bergerak oleng ke kanan-kiri! Mentang-mentang sepi, ia bertingkah seakan jalan sempit ini adalah miliknya. Masih untung kami berdua tidak terjembab akibat ulahnya itu.
Ketika akhirnya kami tiba di depan stasiun (untunglah!), aku dengan segera membuka kotak gitarku dan mulai menyanyikan lagu yang kubuat. Misaki, mengenakan tanktop abu-abu dan rok kotak-kotak selutut, lamat-lamat menemaniku bernyanyi bersama malam ini. Yah, setidaknya, aku tidak hanya diiringi oleh sebatang lilin seperti kemarin malam.
♪ Mou kurai, kao shinai de
Dare mo ga shiawase wo yobu egao
Miete iru no?
Warae nakute mo yeah, yeah
Asu e mo omoi wo mune ni
Akai me wo mitte
Waratte mita no?
Tomorrow never knows... It’s happy line!
(Hari sudah gelap, dan aku tidak bisa melihat wajahmu
Semua orang memiliki kebahagiaan di wajah mereka
Dapatkah kamu melihatntya?
Di dalam hatiku, aku berpikir menuju hari esok
Aku melihat mata merahmu
Apakah kamu mencoba untuk tertawa?
Hari esok tiada yang tahu... Ini adalah ucapan bahagia!) ♪
Petikan terakhir gitarku sontak terhenti ketika aku mendapati seseorang berjalan melintas di depanku. Dia...cowok itu! Cowok yang setiap pagi hanya bisa kuperhatikan dari lantai dua kamarku semata. Aku terus memandangi cowok itu sampai ia lenyap dari pandanganku. Bahkan ketika ia tidak ada lagi di depanku, mataku masih terus mengarah ke tempat terakhir ia terlihat. Tentu saja perilakuku tadi memantik rasa penasaran Misaki.
“Kenalanmu?” tanyanya padaku.
Alih-alih menjawab, aku menyerahkan gitarku ke Misaki dan lalu mulai berlari mengejar cowok itu. Meskipun Misaki sempat protes dan bertanya (lebih tepatnya lagi: berteriak) ke mana aku mau pergi, tapi aku tidak peduli. Apa pun yang terjadi, aku harus bisa mengejarnya! Aku harus dapat berbicara dengannya karena mungkin ini merupakan satu-satunya kesempatanku untuk melakukan hal itu.
Aku terus menderapkan sepatuku menuju ke arah cowok itu berjalan sampai akhirnya kudapati ia tengah melewati sebuah terowongan. Dengan tergopoh-gopoh, aku lantas turut menelusuri terowongan tersebut. Aku sempat berhenti sebentar untuk mengambil nafas dan melihat ke arah mana cowok itu melangkah, dan sebentar kemudian, aku melanjutkan berlari.
Jalan-jalan gravel, toko yang sudah tutup, dan kedai mie udon yang tidak terlalu ramai telah kulewati satu persatu. Nafasku terengah-engah dan kakiku terasa penat, tapi aku tidak berkeinginan untuk berhenti. Tidak, tidak sampai aku bertemu dengan cowok itu! Aku kemudian melintasi pertigaan, dan sesaat setelah aku melewati belokannya, aku kembali ke situ. Benar saja, cowok itu ternyata berbelok, dan ia kini tengah menunggui kereta api lewat. Kesempatan emas! Kakiku dengan segera melaju cepat ke arahnya untuk menyusul cowok itu. Aku mempercepat langkahku saat kulihat pintu palang kereta api sudah kembali membuka. Jangan sampai dia pergi lagi, tegasku dalam hati. Namun, tiba-tiba aku sadar kalau aku sudah terlalu dekat untuk mengerem. Bisa ditebak, tubuhku dengan frontal menabrak punggung cowok itu, membuatnya terjungkal ke aspal. Cowok itu mengerang sejenak tatkala lengannya membentur besi rel kereta api. Dengan ekspresi kesakitan, ia memegangi lengannya itu.
“Aku Amane Kaoru,” ujarku masih dengan nafas tak stabil akibat berlari. Aku sudah sejak lama sekali menantikan pertemuan ini, jadi tanpa membuang waktu, aku segera memperkenalkan diri.
“Apa?” tanya cowok itu kebingungan.
“Aku Amane Kaoru,” untuk kedua kalinya, aku kembali menyebutkan namaku.
“Heh?” cowok itu berseru. Ia tampak semakin bingung. Yang ada di pikirannya sekarang mungkin adalah ‘Ada apa dengan cewek ini?’.
“Aku Amane Kaoru,” aku kembali mengulangi kata-kataku.
“Eh, bagaimana...?”
“Umurku enam belas tahun, tinggal bersama orang tuaku, hobiku adalah musik, dan kepribadianku sedikit cepat emosi,” ucapku bertubi-tubi. Aku maju sedikit demi sedikit, dan sebagai balasan, cowok itu mundur sedikit demi sedikit pula. “Oh ya, aku juga tidak punya pacar!”
“Heh?” cowok itu kembali berseru kaget sesaat setelah aku mengutarakan kalimat terakhir tadi—yang lebih mirip pernyataan suka secara tidak langsung. Namun, aku tidak peduli. Aku memang merasakan hal itu dalam hatiku, dan itulah sebabnya aku terus berbicara. Pokoknya, aku harus membuat ia tahu sebanyak mungkin mengenai diriku dan bagaimana perasaanku terhadapnya!
“Aku selalu memperhatikanmu selama ini,” kataku terang-terangan, “dan aku tidak punya pacar!” aku menegaskan kembali statusku. Kemudian, aku berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Kombinasi antara berlari dan berbicara terus-menerus tanpa henti ternyata memberikan efek yang buruk bagi nafasku.
Melihatku tidak memberondongnya dengan kalimat apa pun lagi, cowok itu kemudian membalas, “Oh, begitu rupanya. Tunggu sebentar, aku....”
“Aku juga belum punya pacar sebelumnya,” potongku cepat, takut kalau ia lantas berubah pikiran mengenaiku (meskipun aku tidak yakin mengenai apa yang ada di dalam pikirannya itu).
“Ya, ya, sebentar dulu...,” ujar cowok itu berusaha menenangkanku. Namun, itu tidak akan berhasil; aku terlalu bersemangat karena sudah dapat berbicara dengannya!
“Binatang favoritku adalah cheetah,” aku melanjutkan, “untuk makanan, aku suka pisang, dan musisi favoritku...,” aku mengangkat tanganku, kemudian mulai menghitung satu persatu, “ada banyak sekali. Harus kumulai dari mana?”
“Kaoru!”
Dengan tergesa, Misaki datang menghampiriku. Ia lantas meraih tanganku, meminta maaf kepada cowok itu, dan lalu cepat-cepat meninggalkannya dalam kondisi masih terduduk di jalan aspal.
“Kenapa?” seruku kepada Misaki setelah kami sudah berbelok di pertigaan. Kenapa, sih, Misaki ini? Apa maksudnya dia ikut campur?
“Apanya yang ‘kenapa’?” balas Misaki. Ia masih terus menuntunku dan memegangi tanganku, tapi dengan segera, aku menampikkan tangannya.
“Jangan menghalangiku!” sergahku kesal. Tentu saja hatiku menjadi dongkol. Setelah akhirnya aku dapat bertemu dengan cowok itu, sepupuku ini justru datang dan menggiringku pergi darinya!
“Apa? Menghalangi?” Misaki menjawab dengan intonasi suara meninggi. “Aku baru saja menyelamatkanmu tadi!”
“Eh?”
“Apanya yang ‘eh?’” balas Misaki. Ia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan berkata, “Kamu barusan terlihat seperti orang bingung, tahu,” aku mendengar ia tertawa kecil, “dan apa maksudnya dengan ‘aku suka pisang?’ Itu sangat tidak profesional!”
Aku terdiam sebentar. Setelah kupikir-pikir, perkataan Misaki ada benarnya juga. Aku justru terlihat seperti orang bodoh saking bersemangatnya tadi. Aduh, jangan-jangan cowok itu justru mengira aku orang aneh! Sambil memikirkan hal itu, aku kemudian beralih dari Misaki dan mulai berjalan mendahuluinya. “Kurasa begitu,” gumamku perlahan. Melihatku berjalan pergi, Misaki kemudian bergegas menyusulku.
“Hei, kamu belum pernah bicara dengan cowok sejak SD, kan?” tanya Misaki saat ia sudah berhasil menjajariku. “Jadi, ada apa dengan cowok itu?”
Pada mulanya, aku tidak menjawab. Namun, ketika kami sudah kembali ke kamarku, aku lantas menceritakan segalanya mengenai cowok itu, mulai dari bagaimana aku selalu memperhatikannya dari lantai dua setiap pagi sampai apa yang kurasakan kepadanya. Sebagai tambahan, Misaki lalu kuminta untuk duduk bersamaku di sisi jendela sampai cowok itu kembali datang di halte bus keesokan paginya. Berdua, yang kami lakukan hanyalah memandangi cowok itu lewat jendela kamar sampai akhirnya kedua temannya datang. Ia lalu mulai bercanda dengan mereka sebagaimana biasanya.
“Ia sepertinya satu SMA denganku...,” komentar Misaki akhirnya setelah melihat cowok itu lebih detail, “tapi aku rasanya tidak mengenalnya.”
“Itu karena kamu sering bolos, Bodoh!” ucapku. Tentu saja. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenal teman sekolahmu kalau kamu tidak pernah masuk?
Misaki tertawa kecil mendengar kata-kataku. “Betul juga,” sahutnya, ”tapi, tapi, seperti yang kubilang, kamu tidak tahu apa-apa tentang dia, kan?”
“Itu karena yang kulakukan hanyalah memperhatikannya dari sini,” jawabku lirih. Sebuah jawaban yang benar-benar menggambarkan keadaanku, karena tentu saja aku tidak akan dapat menemuinya di siang hari. “Aku penasaran, orangnya seperti apa, yah?” aku berkata kepada diriku sendiri sambil terus memandangi cowok itu. “Apa dia jago dalam berselancar?”
Setelah itu, sepi. Misaki tidak menjawab kata-kataku barusan, dan aku tidak mengatakan apa pun lagi. Selama beberapa saat, kami hanya memperhatikan ketiga cowok yang ada di halte bus itu bercanda satu sama lain.
“Kalau begitu...,” ujar Misaki akhirnya, “kenapa tidak kamu pakai saja pakaian yang digantung di bawah itu?”
Apa? Menemui cowok itu dengan mengenakan pakaian seperti itu? “Tidak!” aku menolak cepat-cepat. “Kalau dia melihatku seperti itu, dia akan membenciku!” tambahku memberikan alasan. Kurasa itu wajar; cowok mana yang senang melihat ada cewek yang mendekatinya dengan pakaian aneh seperti itu? Misaki, aku tahu kalau kamu berusaha memberikan saran, tapi sepertinya aku tidak akan bisa melakukan saranmu ini.
Misaki terdiam sejenak setelah aku menyangkal idenya barusan. Kemudian, ia mulai berbicara lagi, “Yah mau bagaimana lagi,” ia menatapku sambil tersenyum, “sudah lama aku tidak ke sekolah, tapi aku akan pergi dan mencari tahu lebih banyak untukmu!”
“Benarkah?” tanyaku tidak percaya. Misaki membalas dengan anggukan mantap. Dasar. Kalau kamu memang berkesempatan untuk berangkat ke sekolah, Misaki, seharusnya kamu menggunakan ksempatan itu untuk belajar!
***
3
Namanya Fujishiro Kouji
Keesokan harinya menjadi hari yang paling menyenangkan sekaligus menyebalkan buatku. Menyenangkan karena Misaki ternyata betul-betul melaksanakan ucapannya kemarin. Bayangkan saja, ia rela membawa sebuah handycam ke sekolah hanya untuk merekam cowok itu supaya dapat dipertunjukkan kepadaku! Lewat pintu kelas yang terbuka sedikit (ralat, lewat pintu kelas yang ia buka sedikit), Misaki mengambil gambar cowok itu di saat pelajaran tengah berlangsung (artinya, dia sama saja bolos). Sedangkan menjadi hari yang menyebalkan karena aku harus pergi ke rumah sakit. Namun, seperti biasa, aku menolak saat Otousan dan Okaasan hendak mengantarku ke sana, padahal aku harus melakukan pemeriksaan badan. Aku memang membenci rumah sakit sejak dulu. Bahkan bisa kubilang rumah sakit merupakan tempat nomor satu yang kubenci sedunia. Lagipula, aku merasa sehat-sehat saja, jadi buat apa ke sana? Penyakit XP, sejauh yang kutahu, memang belum ada obatnya, tapi selama aku tidak terpapar sinar UV, kurasa tidak akan menjadi masalah. Pada akhirnya, Otousan dan Okaasan pergi menemui dokter tanpaku.
Misaki datang ke rumah sore harinya dengan masih mengenakan seragam sekolah, seperti biasa. Sesuai janjinya, ia membawa serta hasil rekaman handycam-nya. Aku dengan segera lantas menyambungkan handycam Misaki dengan TV yang ada di kamarku, dan gambar cowok itu—yang tengah duduk di kursi dekat jendela—langsung tertampang di hadapanku. Sepertinya, ia tidak terlalu antusias mengikuti pelajaran.
“Namanya Fujishiro Kouji,” Misaki mulai memperkenalkan cowok itu. Namun, ia tidak benar-benar menonton bersamaku dan lebih memilih membuka-buka majalah remaja yang sudah lama tak kubaca. “Keren, kan?” tambahnya sambil meraih sebuah kipas angin.
“Fujishiro Kouji,” aku mengulangi dua kata terakhir yang Misaki ucapkan sembari tersenyum. Jadi itu namanya? Sebaiknya aku memanggilnya apa, ya? Fujishiro-san atau Kouji-kun? “Dia sedang tidur, ya?” tanyaku kepada Misaki ketika untuk kesekian kalinya, aku melihat kepalanya terangguk-angguk tanda ia hampir tertidur.
“Tidak, kok,” balas Misaki sambil terus membaca. “Sepertinya, ia terlihat agak bodoh.”
Mataku terus menatap layar TV, bahkan setelah gambar di situ sudah beralih menjadi koridor sekolah. Jadi itu SMA, ya? Ceweknya mengenakan seragam model pelaut dan rok hitam selutut seperti yang dikenakan Misaki, sedangkan cowoknya memakai kemeja putih dan celana panjang hitam seperti yang cowok itu—Kouji—kenakan. “Oh, tempatnya lebih bagus dari yang kubayangkan,” aku mengomentari SMA tempat Misaki bersekolah.
“Betul juga,” kata Misaki, “ini pertama kalinya kamu melihat SMA, kan?”
“He-eh,” aku berkata tanpa menoleh. Tanpa berkedip, aku terus memperhatikan rekaman Misaki yang kembali memperlihatkan interior sekolahnya. “Semua orang terlihat sangat menikmatinya,” ucapku.
“Heh?” Misaki berseru kaget sesaat setelah aku berkata demikian. “Tidak ada gunanya pergi ke tempat seperti itu!”
Misaki akhirnya berhenti mengambil gambar interior sekolahnya dan kembali ke Kouji. Namun, kali ini ia tidaklah sendirian; ada dua cowok lain yang bersamanya. Menyadari hal itu, Misaki lantas melempar majalah yang tengah ia baca dan merosot ke sampingku untuk menjelaskan siapa mereka.
“Well, kelihatannya tiga orang ini selalu bersama-sama,” ujar Misaki menerangkan. Aku mengangguk sejenak, menunggu kata-katanya berikutnya. “Yang ini, temannya yang pertama,” ia menunjuk cowok memiliki rambut panjang yang disemir cokelat, “namanya Onishi Yuuta,” tambahnya. Kemudian, ia beralih ke cowok yang lain. Berbeda dengan yang pertama, kali ini cowok itu berambut hitam dengan gaya spiky, “Dan yang ini, temannya yang kedua, Satsuo Haruo,” ia menambahkan.
Rekaman lantas berganti memperlihatkan Kouji masuk ke WC. Benar-benar deh, Misaki. Apa sih yang kamu pikirkan sampai-sampai menguntit seorang cowok yang hendak ke WC segala? Meskipun begitu, aku tetap dengan sabar terus melihat layar TV, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Kulihat dua orang teman cowok itu—Yuuta dan Haruo—berjalan melewati toilet, dan tak lama berselang, Kouji keluar sambil mengangkat kedua tangannya. “Aku tak yakin dia mencuci tangannya,” komentarku saat menyaksikan adegan itu.
“Sepertinya dia mencucinya,” balas Misaki setelah kami melihat Kouji mengibas-ngibaskan tangannya. Kouji melihat sekeliling, dan saat menyadari kedua temannya ada di dekat situ, ia bergegas menghampiri mereka. Tiba-tiba, ia memegang kepala cowok berambut panjang (Yuuta, ya?), dan—coba tebak—ia menggosok-gosokkan tangannya (yup, tangan yang barusan ia gunakan dari WC) ke rambut Yuuta!
“Ah, mengerikan,” ujarku sambil tersenyum melihat tingkahnya itu. Kouji lantas melakukan hal yang sama kepada Haruo, membuat kedua temannya itu dengan segera langsung mengejarnya. Setelah itu, rekaman berakhir, dan layar TV-ku berubah menjadi biru. Sudah selesai? Cepat juga, ya.
“Nah, demikian perkenalannya,” kata Misaki.
Aku berpikir sejenak mengenai apa yang harus kukatakan untuk menilai Kouji setelah melihat video Misaki barusan. Akhirnya, setelah menimbang-nimbang apa saja perbuatannya sedari tadi, aku sampai pada satu kesimpulan. “Setelah dipikir-pikir,” ujarku, “dia terlihat seperti orang bodoh.”
Misaki langsung menoleh kepadaku begitu aku selesai mengucapkan pernyatan itu. Sepertinya, ia tidak menyangka aku akan mengeluarkan komentar seperti itu terhadap Kouji mengingat aku sangat berkeinginan untuk mengenalnya. Tapi mau bagaimana lagi, kelakuannya memang seperti orang bodoh, sih!
***
Ketika aku pergi keluar malam harinya, aku membawa serta handycam Misaki bersamaku. Aku masih ingin melihat video tentang Kouji yang telah ia rekamkan, dan itulah mengapa sepanjang perjalanan melintasi Yamacho-ri, aku berjalan sambil tertunduk mengamati handycam. Tampak Kouji tengah melewati jalan yang sama denganku, hanya saja, di dalam video itu hari masih siang dan Kouji menggunakan payung karena gerimis (omong-omong, apa Misaki tidak takut handycam-nya rusak, ya?). Senyum kecilku muncul saat melihat gambar Kouji di situ. Aku berjalan di tempat yang sama dengannya, pikirku.
Aku menyempatkan diri untuk mampir ke halte bus yang biasa sepulangnya dari depan stasiun. Tanganku masih memegangi handycam Misaki, dan aku masih memperhatikan tingkah Kouji yang berhasil ia rekam. Handycam itu kini menampilkan Kouji tengah duduk di bangku berwarna biru yang sama dengan yang kududuki. Kemudian, aku melihat ia mengambil botol plastik dan lalu mulai minum dari botol itu. Aku lantas juga meminum sebotol Pocari Sweat yang kubawa dari rumah. Aku melakukan hal yang sama dengannya, pikirku. Setelah itu, aku kembali berkonsentrasi pada handycam Misaki. Namun, saat kusadari baterai handycam tersebut sudah mencapai titik kritis, aku menutup handycam itu dan mematikannya.
Aku kemudian beralih memandangi langit malam yang gelap. Bulan besar yang sudah kuakrabi tampak berada di sana, seakan berbalik memandangiku. Sambil tetap menengadah ke atas, aku mulai menyenandungkan sebuah lagu yang kubuat. Tak lama, aku sudah berinisiatif untuk membuka kotak gitarku dan memainkan lagu tersebut. Lagu itu bisa kubilang masih jauh dari sempurna; liriknya baru kutemukan sebagian dan aku belum memberikan judul baginya. Aku terus bernyanyi sambil memetik gitarku sampai aku menyadari ada seseorang. Seseorang yang tingkahnya sejak tadi kuperhatikan lewat handycam. Orang itu... Kouji! Ia kini tengah berada di atas skuter miliknya dengan mesin dan lampu masih dihidupkan. Di kepalanya, sebuah helm lucu bercatkan bendera Inggris terpasang. Kami saling memandang selama beberapa saat tanpa bersuara, tapi akhirnya aku memberanikan diri untuk menyapanya terlebih dahulu.
“Se...selamat malam,” ujarku gugup. Duh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan?
“Selamat malam juga,” balas Kouji, “kamu cewek yang waktu itu, kan?”
Ah, dia ingat! Ralat, kenapa dia masih mengingatnya? Oh ya, tentu saja; tidak banyak cewek yang menghantamnya dari belakang dan berbicara terus-menerus bagaikan rangkaian gerbong kereta api, jadi tidak heran kalau ia masih mengingatku. “Eh, ya,” kataku membenarkan, “yang waktu itu...maaf, ya,” tambahku. Kalau aku mengingat hal itu lagi, rasanya benar-benar memalukan!
“Tidak mengapa,” jawab Kouji. Setelah itu, ia terdiam selama beberapa saat. “Oh, ya, apa yang kaulakukan di sini?”
“Aku baru pulang dari bernyanyi,” aku menjawab sambil memperlihatkan gitarku. “Aku sering bernyanyi di depan stasiun kereta,” ucapku menambahkan.
“Ah, jadi kamu salah satu dari mereka yang bernyanyi di jalanan?”
“Ya, semacam itulah.”
“Benarkah?” ujar Kouji. Ia lantas mematikan mesin skuter dan lalu menanggalkan helmnya. “Lagu yang kaumainkan tadi bagus juga. Apa judulnya?”
“Aku belum memutuskannya,” jawabku. Seperti yang kubilang, lagu ini belum benar-benar selesai, kan?
Kouji tampak terpana mengetahui aku membuat laguku sendiri. “Jadi kamu yang menulisnya sendiri?” tanyanya kagum, yang kubalas dengan anggukan. “Wah, hebat sekali!”
“Benarkah?” tanyaku gembira. Senang rasanya dipuji oleh seseorang yang selama ini hanya bisa kupandangi dari jauh. Sebagai balasan (dan untuk menyambung pembicaraan), aku lantas bertanya kepada Kouji, “Apa itu...papan seluncur?” Pertanyaan bodoh. Dilihat dari mana pun, tentu saja itu adalah papan seluncur! “Eh...papan seluncurmu keren,” tambahku cepat-cepat.
“Kamu tahu papan ini?” balas Kouji. Ia terlihat senang setelah kupuji seperti itu. “Aku membelinya setelah lama memilih,” ujarnya sambil mengambil papan seluncur itu dari skuternya. Dibawanya papan seluncur itu ke hadapanku, kemudian ia melanjutkan berkata, “Sampai sekarang, masih menjadi yang terbaik bagiku. Yah, meskipun ini barang bekas.”
Aku terdiam menanggapi perkataan Kouji. Ia terlihat bersemangat ketika membicarakan papan seluncur, sama halnya jika akau mulai berbicara tentang lagu. Ah, kuharap pembicaraan kami malam ini yang berawal menyenangkan akan berujung manis.
“Kalau punyamu bagaimana?” Kouji bertanya padaku.
“Eh?”
“Itu juga barang bekas?”
Sedetik kemudian, aku langsung sadar kalau yang Kouji maksudkan adalah gitarku. Sebenarnya, ini bukanlah barang bekas; aku membelinya langsung dari toko. Namun, aku tidak enak kalau mengatakan seperti itu. Salah-salah aku justru dikira sombong. Karena itu, alih-alih menjawab, aku kemudian memasukkan gitarku kembali ke dalam kotaknya dan lalu menyenderkannya ke motor Kouji supaya ia tak bertanya-tanya lagi. Selepas itu, aku kembali duduk sementara Kouji membeli sesuatu di mesin penjual otomatis. Ia kemudian duduk di bangku yang sama denganku setelah mendapatkan minumannya.
Jantungku berdetak dua kali lebih kencang di saat Kouji menghempaskan diri di bangku itu. Ya, aku sadar aku kini berada dalam situasi apa: dalam keremangan malam yang sunyi, aku tengah duduk berdua bersama Kouji. Fujishiro Kouji, cowok yang selama ini hanya bisa kupandangi dari jauh. Cowok yang ingin sekali kuajak berbicara berdua saja, hanya saja baru kali ini aku berkesempatan untuk melakukan hal itu (jangan hitung kejadian yang kemarin; itu sama sekali bukan bicara berdua!). Dan yang paling penting, Kouji—yang pernah kubilang telihat seperti orang bodoh itu—adalah cowok yang kusukai. Aku memang memendam perasaan itu; aku selalu memperhatikannya, berusaha mengetahui tentang dirinya, dan—seperti sekarang ini—menjadi gugup ketika bersama dengannya.
Selama beberapa menit, kami hanya terduduk dalam diam. Kouji hanya menatapi skuternya sambil memegangi minuman, sementara aku... hem, pada awalnya aku memang memilih untuk melihat ke arah lain, tapi tak lama kemudian, mataku sudah beralih memperhatikan wajahnya. Aku belum pernah dapat melihat wajah Kouji sampai sedekat ini, dan ketika aku melakukan hal itu, aku merasakan mukaku menjadi panas!
“Kamu tinggal di sekitar sini?” Kouji tiba-tiba bertanya sambil menoleh, membuatku terkaget. Dengan segera, aku mengalihkan pandanganku supaya tidak terlihat kalau aku memandanginya sedari tadi.
“Aku tinggal di rumah yang berada tinggi di sana,” jawabku sembari menunjuk rumahku sendiri.
“Di sana? Benarkah?” tanya Kouji heran. “Setiap hari aku lewat jalan ini, loh!”
“Ya, aku tahu.”
“Hah? kamu tahu?” untuk kedua kalinya, Kouji tampak terkejut. “Oh, ya, kamu sering melihatku dari atas, ya....”
“He-eh,” balasku.
Kouji terkekeh sejenak setelah aku menjawab kalimatnya. “Sedikit memalukan juga,” katanya, “mulai sekarang, aku tidak bisa melakukan hal aneh lagi,” ia menambahkan sembari memandang ke arahku.
Dipandangi seperti itu membuat dadaku kembali berdegup-degup. Tidak, aku tidak sanggup memandangi wajah tersenyum itu; aku terlalu malu untuk melakukannya. Karena itu, aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, berusaha agar mataku tidak menatap mata Kouji. Aku tidak lagi memiliki kata-kata untuk kuungkapkan, dan kurasa Kouji juga tidak. Jadilah kami duduk di bangku halte ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak mengapa, bagiku, begini saja sudah cukup. Dapat duduk bersampingan dengan Kouji saja rasanya sudah dapat membuatku sangat bahagia! Seandainya saja keadaan seperti ini dapat berlangsung terus....
Piip...piip...piip....
Suara itu! Kenapa alarm itu harus berbunyi di saat-saat seperti ini, sih? Aku memang berkeinginan untuk duduk di sini lebih lama lagi, tapi aku tahu konsekuensinya jika aku melakukan hal itu. Kumatikan alarm jam tanganku, dan dengan berat hati, aku kemudian berkata kepada Kouji, “Baiklah, aku harus segera pergi.”
“Eh? Ya sudah kalau begitu....”
Aku lantas beranjak dari bangku dan mengambil kotak gitarku yang tersandar di skuter Kouji. Kemudian, aku mengucapkan salam perpisahan singkat dengan cowok itu sebelum akhirnya berjalan meninggalkannya. Namun, baru beberapa langkah berjalan, aku mendengar Kouji memanggilku, membuatku menghentikan langkah dan berbalik ke arahnya.
“Kalau aku bisa, aku akan datang.” seru Kouji dari halte bus itu, “ke street performance-mu.”
Apa? Kouji hendak melihatku tampil? Hatiku serasa mau meledak saking senangnya mendengar hal itu, dan senyumku langsung terkembang lebar. “Jangan hanya bilang tapi tidak datang!” balasku.
Mendengarku berkata seperti itu, Kouji tertawa perlahan. “Kalau sudah libur, aku pasti akan datang!” ia kembali menjawab.
Wajahku kembali menampakkan senyum; aku tahu itu. Kuanggukkan kepala sekali tanda setuju, dan Kouji juga mengangguk memberikan kepastian. Ini merupakan sebuah janji tak terucap antara aku dan dia bahwa kami akan bertemu kembali! Aku lantas berbalik untuk melanjutkan perjalananku ke rumah. Namun, hanya selang beberapa langkah, aku kembali menoleh ke belakang untuk melihat sosok Kouji untuk terakhir kalinya. Dapat kulihat ia tengah melambaikan tangannya padaku, dan aku pun lantas membalas lambaiannya sebelum akhirnya beranjak pergi.
Aku belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Harus kuakui, malam ini adalah malam paling indah dari seluruh malam yang telah kulalui. Dan karena dialah—Fujishiro Kouji—aku dapat merasakah malam seindah ini. Entah untuk keberapa kalinya seulas senyum kembali terlukis di wajahku, dan kemudian, aku berlari menuju rumah dengan diliputi oleh kegembiraan. Percakapan kecil kami malam ini memiliki akhir yang menyenangkan seperti harapanku.