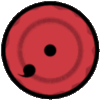Archive for 2012
Sabtu, 28 Januari 2012
Internet, Komputer, mainan, bisnis internet, busana, hanphone, muslim, buku, blog, website, usaha, balckberry, androin, laptop, modem, teknologi, Nasional, Ekonomi, kesehatan, hiburan, hu
Sabtu, 21 Januari 2012
~Afterstory~
Kamakura, 2 Desember 2006
Untuk Kaoru,
Hai, Kaoru. Apa kabar? Tanpa terasa, satu tahun sudah berlalu sejak kamu meninggalkan kami. Aku sendiri kini sudah lulus dari SMA, dan—tidak seperti kedua sahabatku—aku memutuskan untuk tidak kuliah. Alasanku ada tiga: aku tidak cukup pandai, aku tidak memiliki biaya, dan terakhir, aku ingin mengejar impianku menjadi peselencar profesional. Ya, Kaoru, aku kini sadar kalau kata-katamu benar sepenuhnya. Itu, loh, yang waktu di pantai itu. Waktu itu, kamu pernah bilang ke aku kalau aku dapat melakukan apa pun dan bahwa aku pasti bisa menemukan apa yang ingin kulakukan, kan? Sekarang, aku sudah menemukannya, Kaoru. Aku telah menemukan apa yang selama ini menjadi impianku: dibayar hanya untuk mengendarai papan selancar di atas ombak! Perusahaan selancar itu telah mengukuhkan kontraknya padaku, dan kini, mereka menjadi sponsor penuhku. Kalau tetap seperti ini, tidak menutup kemungkinan aku akan memperoleh sponsor-sponsor baru lagi!
Impian, ya...?
Kaoru, ada satu hal yang ingin kuberi tahu padamu. Tidak lama setelah kau pergi, lagumu menjadi hits dan berada di puncak tangga lagu selama beberapa pekan. Mereka memutar lagumu itu di mana-mana—di radio, pusat perbelanjaan, restoran, dan bahkan kereta api. Seandainya saja kamu masih di sini, Kaoru, aku yakin kamu pasti akan meloncat-loncat kegirangan. Kedua orang tuamu juga selalu memutar lagu ciptaanmu itu di restoran mereka. Kalau aku mampir ke sana, suara yang pertama kali kudengar pasti adalah suaramu yang tengah bernyanyi. Selain itu, ketika aku masih di sekolah, lagumu juga terkadang diputar pada saat makan siang. Aku tidak tahu kalau sekarang, tapi kata Misaki, mereka masih sering memutarnya, kok!
Kaoru...aku merindukanmu....
Sudah setahun, Kaoru. Satu tahun sudah aku tidak melihat wajahmu (haha, aku jadi ingat waktu mencubit pipimu dan mengatakan wajahmu aneh). Satu tahun sudah aku tidak mendengar suaramu. Tahukah kau, Kaoru, apabila aku mendengar lagumu, aku merasakan perasaan senang dan sedih mengalir dalam hatiku. Senang karena kamu pada akhirnya dapat mewujudkan impianmu untuk merilis CD debutmu sendiri dan menjadi terkenal (bahkan kabarnya, ada sebuah situs penggemarmu di internet!). Sedangkan sedih karena lagu ini mengingatkanku padamu. Ya, Kaoru, jika aku mendengarkan lagu ini, wajahmu yang lucu itu pasti langsung terbayang di benakku. Begitu pula suaramu yang merdu dan enak didengar. Kaoru, hatiku rasanya perih saat menyadari bahwa aku tidak dapat lagi bertemu dengan pemilik wajah dan suara itu. Kamu.
Ah, Kaoru... Aku mencintaimu. Sampai kapan pun, perasaan ini tetap tak akan berubah. Sampai kapan pun, Kaoru, kamu tetap akan menempati ruang istimewa di dalam relung hatiku. Aku masih akan selalu mengingat saat-saat kita makan bakpau panas bersama atau main air hockey di Yokohama. Begitu pula saat di rel kereta api itu; merupakan suatu hal yang mustahil bagiku untuk melupakannya!
Beristirahatlah dengan tenang, Amane Kaoru. Ah, bukan. Beristirahatlah dengan tenang, kekasihku.
Kouji
***
Kamakura, 2 Desember 2006
Untuk Kaoru,
Osh, Kaoru! Baik-baik saja, kan? Wah, tiba-tiba saja sudah satu tahun, ya? Terakhir kali aku melihatmu, kamu tengah terbaring di dalam peti yang dipenuhi oleh bunga matahari. Waktu itu kamu kelihatannya cantiiiiik sekali! Matamu yang terpejam itu juga terkesan damai. Kaoru, kuharap engkau tenang di sana!
Kaoru, sekarang aku sudah kelas tiga. Itu berarti, sebentar lagi aku akan menghadapi ujian kelulusan. Benar-benar bikin frustrasi! Aku harus masuk sekolah setiap hari, dan baik Ojisan maupun Obasan akan menasihatiku kalau tahu aku bolos. Pada awalnya memang berat, sih. Kalau sudah capek belajar, aku sering menghempaskan diriku di kasur dan menyetel lagumu untuk refreshing. Dan Kaoru, begitu aku mendengar suaramu, entah mengapa tiba-tiba saja semangatku kembali lagi. Mungkin karena aku termotivasi oleh semangatmu, ya? Kau tahu, kan, semangat untuk tetap melangkah dan meraih impian. Pada akhirnya, semangatmu itu mengantarkanmu menuju kesuksesan! Ya, Kaoru, lagumu menjadi hits dan diputar di berbagai tempat. Sayang sekali kamu sudah harus pergi sebelum melihat lagumu melejit.
Oh ya, Kaoru, aku masih sering mampir ke rumahmu sepulang sekolah, loh. Biasanya aku ke sana untuk numpang makan malam (kau kan tahu bagaimana rasanya masakan Ojisan?). Seusai makan, aku biasanya akan melihat kamarmu. Kamar itu, Kaoru...banyak kenangan manis tercipta di sana. Kau ingat waktu kamu mengajakku melihat Kouji untuk pertama kalinya dari balik tirai beralumunium? Begitu pula waktu aku menunjukkan video Kouji kepadamu, kau ingat kan? Perlu usaha keras bagiku untuk merekamnya, loh! Dan kalau kuedarkan pandanganku, Kaoru, maka aku akan menemukan kotak gitarmu berdiri di samping tempat tidur.
Kotak gitar itu....
Benda itu dulu selalu kautenteng setiap malam ke depan stasiun, kan? Terkadang, kamu mengajakku ikut ke stasiun untuk mendengarkan nyanyianmu. Aku sampai hafal kebiasaanmu sebelum mulai bermain: menyalakan sebatang lilin terlebih dahulu! Setelah itu, kamu akan mulai memetik gitarmu sambil memainkan lagu yang kamu buat.
Tapi itu dulu, ya kan?
Sekarang, gitar dalam kotak itu tidak ada lagi yang memainkannya. Terkadang, Kaoru, aku kangen mendengar suaramu secara langsung, bukan suaramu dari CD ini. Kalau bertemu scara langsung, kita bisa bercakap-cakap tentang banyak hal; mulai dari Kouji sampai cowok yang kusukai di sekolah. Tapi biarlah. Apa yang berlalu biarlah berlalu, yang penting, kini kamu sudah tenar, Kaoru!
Selamat, ya, dan semoga kamu senang di atas sana.
Misaki
***
Kamakura, 2 Desember 2006
Untuk Kaoru,
Hai, Kaoru. Bagaimana kabarmu di sana? Okaasan dan Otousan di sini baik-baik saja, jadi kami harap kamu juga sehat. Sudah setahun sejak kepergianmu, dan suasana rumah rasanya menjadi sepi sekali. Tidak ada lagi suara permainan gitar dari lantai atas sebagaimana biasanya. Tidak ada lagi suaramu menuruni tangga atau membuka pintu gerbang seperti yang dulu selalu kaulakukan setiap malam. Sungguh, rasanya berbeda sekali!
Kaoru, mungkin kamu sudah tahu dari Kouji dan Misaki, tapi kami tetap akan memberitahumu ini. Tidak lama setelah kau pergi, CD-mu dirilis, dan—coba tebak. Kini, lagumu populer di mana-mana! Otousan dan Okaasan sangat bangga padamu. Kami memutar lagu ciptaanmu di restoran sehingga semua orang yang datang selalu dapat mendengarnya. Menakjubkan, kan? Kini semuanya tahu kalau kami adalah orang tua dari penyanyi terkenal itu!
Kaoru, kami hanya ingin kau tahu kalau kami di sini baik-baik saja. Pada awalnya, rasanya memang berat untuk melepasmu. Kami sering duduk-duduk di ruang makan sambil membicarakan banyak hal tentang kamu. Bagaimana dulu kamu merengek ingin keluar waktu kecil. Bagaimana dulu kamu menunjukkan kepada kami lagu ciptaanmu yang pertama. Sejak saat itu, kamu mulai sering keluar malam, ya kan? Dan bagaimana kita bersama-sama pergi ke studio rekaman untuk membuat CD debutmu setahun lalu. Ah, ya, Kaoru, semua itu adalah ingatan yang menyenangkan tentang dirimu. Namun, kehidupan harus terus berjalan. Kami pada akhirnya harus rela membiarkanmu pergi, dan itulah yang kini tengah berusaha kami lakukan.
Satu hal lagi, Kaoru, Otousan dan Okaasan tidak akan pernah melupakanmu. Kamu akan selalu menjadi gadis kecil kami hingga kapan pun. Ya, Kaoru, kamu adalah gadis kecil yang kini sudah beranjak remaja dan memperoleh impiannya lewat usahanya sendiri. Gadis remaja itu telah membuat kami, orang tuanya, bangga dengan apa yang telah dicapainya.
Selamat tinggal, Kaoru. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu saat kelak.
Otousan dan Okaasan
Tag :// Articles,
Tag :// YUI
shiro Kouji. Tujuh belas tahun. Belum lama ini, aku bertemu dengan seorang cewek bernama Amane Kaoru. Pertemuan kami tidak bisa dibilang menyenangkan. Pada saat itu, cewek itu menabrakku sehingga lenganku membentur bantalan rel kereta api, dan ia lantas mulai berceloteh mengenai dirinya sendiri—mulai dari temperamennya sampai makanan kesukaannya, pisang.
Saat itu, aku tidak begitu memedulikan cewek itu. Sungguh! Aku menganggap cewek itu hanya sebagai angin lalu saja. Namun, pada suatu malam menjelang musim panas, aku bertemu kembali dengan cewek itu. Kuperhatikan ia tengah bersenandung sembari memainkan gitar, dan aku langsung tertarik mendengarnya. Ternyata, ia cukup jago bermusik juga! Kami akhirnya menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang malam itu, dan dari situlah aku tahu kalau ia ternyata selama ini memperhatikanku dari kamarnya yang terletak di lantai dua rumahnya. Aku lantas berjanji untuk datang ke street performance-nya ketika libur musim panas telah tiba.
Hari pertama liburan, aku langsung membawa motorku ke depan stasiun tempat Kaoru tampil. Namun, aku tidak melihatnya memainkan gitar dan justru duduk di atas trotoar. Katika aku bertanya ada apa, ia menjawab kalau tempatnya biasa tampil telah diambil alih oleh seseorang. Aku lantas mengajaknya untuk tampil lain, dan pilihanku jatuh pada Yokohama. Kaoru tampak menikmati saat-saat berdua kami. Begitu pula aku. Aku baru sadar kalau ia ternyata adalah sosok cewek yang menyenangkan setelah menghabikan banyak waktu bersamanya. Sepulangnya dari Yokohama, ketika kami berada di atas motor, Kaoru menyandarkan kepalanya di punggungku, dan suatu perasaan aneh langsung membuatku berdegup.
Aku ingin menunjukkan keindahan panorama matahari terbit yang biasa kulihat sebelum berselancar, karena itu aku mampir di pantai sebelum mengantarkan Kaoru pulang ke rumahnya. Namun, entah kenapa ia bertingkah aneh dan justru minta pulang begitu aku memintanya tinggal. Maksudku, apa salahnya melihat matahari terbit bersama? Karena Kaoru bersikeras, aku lalu memboncengkanya dengan skuterku. Ia langsung berlari menuju rumahnya sesaat setelah kami tiba, dan ia bahkan meninggalkan kotak gitarnya! Aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya ia sangat terburu-buru. Ketika aku mengejar Kaoru untuk mengembalikan kotak gitarnya, ia justru membanting pintu di hadapanku. Aku lalu menaruh kota gitar Kaoru di samping pintu, kemudian, masih dengan pikiran dipenuhi tanda tanya, berjalan turun. Ketika aku hendak menaiki skuterku, aku bertemu dengan seorang cewek berkaca mata yang kukenali sebagai adik kelasku. Ia bertanya apakah aku melihat Kaoru, jadi kujawab saja aku barusan mengantarkannya pulang. Respons adik kelasku itu—Misaki—jauh di luar bayanganku; ia terlihat kaget sekaligus murka. Misaki lalu berkata kalau Kaoru mengidap penyakit, dan dia dengan berang bertanya padaku bagaimana aku akan bertanggung jawab seandainya ia mati.
Pada awalnya, aku tidak begitu mengerti. Namun, aku lantas mulai mencari-cari penyakit macam apa yang membuat penderitanya harus menjauhi sinar matahari. Kesimpulan itu kudapat setelah aku melihat tiga hal: kebiasaan Kaoru keluar malam, reaksi cemasnya ketika aku berkata ingin melihat matahari terbit bersamanya, dan kemarahan Misaki setelah aku mengantarkan Kaoru pulang ketika matahari sudah terbit. Dari situlah aku mengetahui kalau ia menderita penyakit kulit bernama XP, yang kemudian dibenarkan oleh Misaki.
Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi melihat Kaoru bermain gitar di depan stasiun sebagaimana biasanya. Itulah sebabnya aku mampir ke rumahnya pada suatu malam, tapi ia justru membentakku dan menyuruhku pulang. Setelah itu, berdasar yang kudengar dari Misaki, ia mengurung diri di kamarnya dan hanya keluar ketika makan malam saja. Aku jadi merasa bersalah melihat keadaan Kaoru yang seperti itu. Itulah sebabnya aku lantas mencari cara supaya ia dapat kembali bersemangat dan—terutama—mau menemuiku lagi. Pada akhirnya, aku menemukan sebuah solusi ketika melihat iklan tawaran rekaman. Namun, karena biaya pendaftarannya yang mencapai 200.000 yen, aku mulai berpikir untuk memperoleh uang tambahan. Hal pertama yang kulakukan adalah menjual papan luncurku. Agak sayang juga, tapi ketika aku ingat aku melakukan ini demi Kaoru, hatiku langsung merelakan papan itu. Selain itu, aku juga bekerja paruh-waktu. Pekerjaan pertamaku adalah mencuci sejumlah kapal feri milik perusahaan penyeberangan. Aku memperoleh 20.000 yen dari situ. Lumayan.
Suatu ketika, aku mengalami kejadian yang tak diduga-diduga; ayah Kaoru mengajakku makan malam di rumah mereka! Aku lalu menyampaikan rencanaku kepada Ojisan, dan dia setuju. Malam harinya, aku memberi tahu Kaoru mengenai brosur yang berisikan tawaran rekaman itu. Kaoru sempat ragu pada mulanya, tapi ia kemudian menyanggupinya.
Setelah makan malam, kami berdua lalu berjalan-jalan keluar. Merupakan suatu hal yang melegakan bagiku saat melihat Kaoru mau berbicara lagi denganku. Kami terlibat dalam pembicaraan kecil kala itu, dan begitu aku bilang aku menyukainya dan akan menemuinya pada malam hari, aku melihat ia menangis. Aku lalu mencubit kedua pipinya supaya wajahnya menampakkan eksprsi tersenyum. Pada saat itu, aku baru menyadari kalau wajah Kaoru ternyata lucu—dan juga manis. Tanpa kusadari, beberapa detik kemudian bibirku sudah mendarat di atas bibirnya.
Aku jadi semakin sering mengunjungi Kaoru pada malam hari, seperti kata-kataku. Namun, aku juga tahu kalau ia tengah mempersiapkan diri untuk CD debutnya. Itulah sebabnya beberapa minggu menjelang rekaman, aku memutuskan untuk tidak berkunjung supaya ia bisa konsentrasi berlatih. Namun, setelah berhari-hari aku tidak mendegar kabar apa pun dari Kaoru, Misaki membawa kabar yang tidak mengenakkan mengenai dirinya pada suatu ketika. Kata Misaki, kondisi Kaoru memburuk. Ia kini tidak bisa menggerakkan tangan kirinya. Aku langsung pergi untuk membesuk Kaoru di rumah pada malam harinya, dan tiba-tiba saja ia lantas bercerita mengenai pertama kali ia melihat diriku, yakni ketika aku mengagumi sebua papan seluncur yang tersandar di dekat halte bus. Aku jadi malu sendiri kalau mengingat kejadian itu karena dimarahi oleh pemilik papan seluncur itu. Lebih-lebih, Kaoru ternyata juga melihatku, rasa maluku jadi berlipat ganda!
Beberapa hari setelah kedatanganku itu, hari besar Kaoru tiba. Aku, Ojisan, Obasan, dan Misaki berbondong-bondong mengantarkannya menuju perusahaan rekaman yang berada di Tokyo. Sesampainya di sana, Kaoru lantas meminta baik aku mapun Ojisan untuk tidak melihatnya rekaman karena merasa gugup. Aku sedikit tidak rela pada awalnya, tapi karena Obasan memaksa, kami akhirnya keluar juga. Selama rekaman, Ojisan terlihat gelisah. Menurutnya, Kaoru bukanlah seorang profesional, jadi ia takut kalau-kalau putrinya itu berulang kali melakukan kesalahan. Namun, aku tahu pasti kalau Kaoru adalah seorang musisi profesional. Buktinya, waktu di Yokohama ia justru semakin bersemangat ketika orang lain mengerumuninya. Kalau orang biasa pasti sudah gemetar, kataku kepada Ojisan saat itu. Aku sendiri sangat yakin dengan kemampuan menyanyi Kaoru. Suatu saat kelak, ia pasti akan menjadi seorang bintang besar, dan baik stasiun radio, stasiun televisi, maupun orang-orang pasti akan berebut untuk memperoleh CD-nya.
Sekitar tiga bulan kemudian, CD Kaoru akhirnya dirilis. Aku dan Misaki menjadi orang pertama yang membeli CD itu, baru kemudian diikuti oleh Ojisan dan Obasan. Seperti perkiraanku, lagu Kaoru menjadi hits, dan berbagai stasiun radio memutarnya berulang kali. Namun, sayang sekali Kaoru tidak bisa melihat mimpinya menjadi kenyataan. Ia meninggal dua bulan silam, meninggalkan kenangan yang tak ada habisnya dan lagu yang amat ia sukai.
♪ Dakara ima ai ni yuku sou kimetanda
Pocket no kono kyoku wo kimi ni kikasetai
Sotto volume wo agete tashikamete mita yo
Oh Good-bye days, ima
kawaru ki ga suru kinou made ni so long
Kakkoyokunai yasashi sa ga soba ni aru kara
La la la la la with you
Katahou no earphone wo kimi ni watasu
Yukkuri to nagarekomu kono shunkan
Umaku aisete imasu ka?
Tama ni mayou kedo
Oh Good-bye days, ima
kawari hajimeta mune no oku alright....
Kakkoyokunai yasashi sa ga soba ni aru kara
La la la la la with you
Dekireba kanashii omoi nante shitakunai
Demo yatte kuru desho?
Sono toki egao de “Yeah hello! my friend” nantesa
Ieta nara ii no ni...
Onaji uta wo kuchizusamu toki soba ni ite I wish
Kakkoyokunai yasashi sa ni aete yokatta yo
La la la la Good-bye days....
(Karena itu, aku akan menemuimu sekarang. Itulah yang kuputuskan.
Aku ingin kamu mendengarkan nada yang kubawa dalam kantungku ini
Perlahan, aku menaikkan volume, memastikan bahwa nada itu kubawa
Oh, Selamat tinggal hari-hari,
Sekarang, aku merasakan berbagai hal mulai berubah, aku mengucapkan sampai jumpa hingga kemarin
Karena sebuah kebaikan yang tidak keren sudah berada di sisku
La la la la la denganmu
Aku memberikan satu sisi earphone-ku kepadamu
Perlahan, momen ini mengalir melewatimu.
Dapatkah kamu benar-benar mencintaiku?
Meskipun terkadang aku tersesat.
Oh, Selamat tinggal hari-hari,
Sekarang berbagai dalam hatiku mulai berubah. Baiklah...
Karena sebuah kebaikan yang tidak keren sudah berada di sisiku.
La la la la la denganmu.
Kalau bisa, sebenarnya aku tidak ingin merasakan kesedihan.
Tapi mereka akan terus mendatangiku, kan?
Pada saat seperti itu, kalau aku hanya mengucapkan, “Yeah,halo, Temanku sambil tersenyum,
Kelihatannya akan lebih bagus kalau begitu.
Pada saat kita mendengungkan lagu yang sama, aku ingin kau berada di sisiku.
Aku senang kita dapat saling bertemu, meskipun dengan sebuah kebaikan yang tidak keren.
La la la la, Selamat tinggal hari-hari....) ♪
Catatan:
Ojisan: Paman/Oom
Obasan: Bibi/Tante
Tag :// Articles,
Tag :// YUI
Terakhir
Goodbye Days
Sekitar satu setengah bulan kemudian, hari besarku akhirnya tiba juga. Ya, hari ini adalah hari ketika aku akan pergi ke studio rekaman untuk membuat CD debutku. Aku sudah berlatih secara intensif akhir-akhir ini, jadi aku yakin sekali dengan kemampuan menyanyiku. Namun, tetap saja aku merasa sedikit gugup. Bagaimana kalau ketika rekaman nanti, suaraku tidak keluar? Ah, tidak mungkin. Sampai sekarang pun aku masih berbicara, kok. Tapi, bagaimana kalau orang di perusahaan rekaman memintaku untuk bermain gitar? Atau bagaimana kalau tiba-tiba aku ambruk ketika bernyanyi? Atau bagaimana kalau... ah, sudahlah, Kaoru! Tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi, ujarku berusaha menenangkan diri. Setelah agak tenang, aku lalu beranjak ke bawah untuk menemui Otousan yang tengah memanaskan mobil. Untunglah perusahaan rekaman itu buka hingga larut malam sehingga kami bisa berangkat setelah petang.
Setelah merasa siap dengan semuanya, kami lantas berangkat ke Tokyo tempat di mana perusahaaan rekaman itu berada. Yang kumaksud dengan kami di sini bukan hanya aku dan Otousan saja, melainkan juga Okaasan, Kouji, dan bahkan Misaki. Mobil Otousan yang tidak begitu besar sampai penuh karena harus menampung lima orang sekaligus. Misaki sendiri selama perjalanan tidak henti-hentinya bercerita banyak hal mengenai Tokyo. Menurutnya, Tokyo adalah kota besar yang sibuk, dan ketika malam tiba, kota itu akan diterangi oleh berbagai lampu yang bahkan lebih banyak daripada Yokohama. Cerita Misaki itu membuatku penasaran. Apalagi Kouji juga bercerita sedikit mengenai Tokyo Tower yang terkenal itu. Ah, aku jadi ingin cepat-cepat sampai di sana!
Kami sampai di Tokyo beberapa jam kemudian (akhirnya!), dan aku langsung membuktikan kebenaran kata-kata Misaki dan Kouji. Tokyo benar-benar cantik, lebih cantik dari Yokohama. Banyak gedung-gedung besar dan berbagai lampu neon berwarna-warni di sekeliling jalanan. Namun, yang membuatku terkagum adalah Tokyo Tower yang tadi sempat disinggung-singgung Kouji. Menara itu benar-benar cantik, apalagi saat badannya bermandikan cahaya lampu berwarna merah dan kuning seperti sekarang ini! “Wah, indah sekali!” Spontan, aku berseru terkagum ketika melihat menara itu.
“Kamu tidak perlu kaget begitu, kan?” kata Otousan sambil tertawa kecil. Aku sendiri hanya mengulum senyum mendengar kata-kata Otousan. Biar saja! ujaku dalam hati. Toh ini pertama kalinya aku melihat Tokyo Tower. Cewek Jepang berumur enam belas tahun lain mungkin sudah sering melihat atau bahkan mengunjungi menara itu, tapi karena aku baru kali ini melihat Tokyo Tower secara langsung, jadi apa salahnya mengaguminya?
Karena ini merupakan kunjungan pertamaku di Tokyo, Otousan memutuskan untuk terlebih dahulu berputar-putar mengelilingi kota itu. Misaki dan Okaasan menerangkan berbagai macam hal setiap kali aku menanyakan sesuatu yang menarik perhatianku, meskipun Misaki sebenarnya lebih banyak bercerita tanpa kuminta. Namun, pengenalan terhadap kota Tokyo itu tidak bisa berlangsung lama karena aku masih harus pergi ke perusahaan rekaman untuk membuat CD debutku. Bukankah tujuan awal kami datang ke Tokyo memang untuk itu? Itulah sebabnya aku lantas meminta Otousan untuk mengarahkan mobil menuju studio rekaman itu. Aku tidak ingin perusahaan itu sudah keburu tutup saat kami tiba di sana hanya karena kami keasyikan melihat-melihat kota ini!
Begitu kami menjejakkan kaki di perusahaan rekaman itu, aku langsung terkesan dengan interiornya. Dinding dan lantainya terbuat dari kayu mahoni coklat muda, memberikan kesan hangat dan homy bagi siapa pun yang memandangnya. Namun, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan studio rekaman yang dimiliki perusahaan tersebut. Berbagai peralatan rekaman yang terlihat canggih dan mahal tertampang di ruangan itu. Sekumpulan orang yang menjadi band pengiringku terlihat tengah berlatih di dalam ruang rekaman tempat aku akan bernyanyi sebenatar lagi. Dan di sana, di tengah-tengah ruang rekaman, sebuah mikrofon berdiri tegak—seakan-akan menyambutku untuk mulai berjalan menuju impianku.
“Wow, seperti album perdana saja,” komentar Misaki setelah menelusuri studio rekaman tempat kami berada sekarang. Di tangannya, terdapat handycam yang sengaja ia bawa dari rumah. Handycam itu tadinya akan ia pakai untuk mengambil gambarku ketika sedang rekaman, tapi entah kenapa tiba-tiba saja aku jadi tidak setuju. Rasanya, aku akan menjadi gugup kalau dia mensyutingku, dan tentu saja itu akan memengaruhi performaku! Sekarang pun sebenarnya aku mulai disergap rasa gugup. Ini adalah batu loncatan menuju impianku, jadi merupakan suatu hal yang wajar kalau aku merasa seperti itu, kan?
“Semuanya akan baik-baik saja,” ucap Kouji menenangkanku. Aku menelan ludahku sejenak setelah mendengar kata-kata Kouji. Setelah itu, aku mengangguk perlahan. Aku berusaha meyakinkan diriku untuk meyakini kata-kata Kouji, yakni semua ini akan berjalan lancar. Ya, aku hanya perlu percaya akan hal itu, dan semuanya pasti akan baik-baik saja!
Lima menit kemudian, seorang staf dari perusahaan rekaman masuk ke studio dan memberi tahu kami agar bersiap karena proses perekaman akan segera dimulai. Hatiku semakin berdebar dan perasaanku semakin tak karuan. Tenang, Kaoru, tenanglah. Kalau kamu gugup seperti ini, bisa-bisa kamu mengacaukan semuanya. Karena itu, bertenanglah....
“Semoga berhasil,” Otousan turut memberikan dukungan kepadaku. Kemudian, ia berjalan menjauhiku untuk duduk di sofa yang memang tersedia di ruang studio rekaman. Otousan mengangkat tangan kanannya untuk membetulkan rambut, setelah itu melanjutkan berkata, “Kami akan melihatnya dari sini, jadi....”
“Aku mulai gugup, jadi tolong pergilah,” selaku. Jujur saja, perbuatan Otousan itu sama sekali tidak membantuku meredakan ketegangan. Justru sebaliknya; kalau ia menontonku bernyanyi, aku malah akan semakin gugup!
“Apa?”
“Tolonglah,” pintaku.
Otousan terlihat tidak rela dengan pengusiranku barusan.
“Kamu...,” ujarnya sambil mengarahkan telunjuknya kepadaku, “bahkan hingga sekarang, kamu tidak membiarkan kami mendengarnya?”
“Tolong dengarkan kata-katanya, Ojisan,” sergah Kouji. Ia mengambil tempat duduk di samping Otousan, lalu setelah itu berkata kepadanya, “Aku yang akan menontonnya, jadi...”
“Kamu juga, Kouji, pergilah,” kataku sambil tersenyum kecil.
“Heh? Aku juga?” seru Kouji. Dapat kulihat tangannya kini menunjuk pada dirinya sendiri.
“Akan lebih baik kalau kau mendengarnya setelah CD-nya dirilis,” balasku, masih sambil memasang tampang tersenyum.
“Tapi kenapa...?”
“Baik, baik, ayo kita semua pegi,” tiba-tiba Okaasan mengambil tindakan dengan mengajak baik Otousan maupun Kouji berdiri. Ia menggiring keduanya menuju pinu keluar dengan tangan kanan sementara tangan kirinya merengkuh pundak Misaki.
“Aku juga?” tanya Misaki
“Tidak apa-apa, ayo kita pergi,” kata Okaasan lagi. Sebentar kemudian, mereka bertiga sudah keluar dari studio rekaman, meninggalkanku berdua dengan staf perusahaan rekaman. Baguslah. Aku jadi bisa fokus pada rekamanku.
“Kalau begitu, bisa kita mulai sekarang?” tanya staf itu kepadaku. Aku mengangguk sebagai jawaban, dan ia lantas mengantarkanku masuk ke dalam ruang rekaman. Dadaku berdebar semakin keras seiring dengan langkahku. Aku menarik nafas panjang supaya dapat mengontrol diri. Tenang, Kaoru. Yang perlu kamu lakukam hanyalah menyanyi seperti biasa, itu saja! Kamu tidak perlu mengkhawatirkan instrumen, semua itu sudah diurus oleh band pengiring. Kamu sudah sampai hingga sejauh ini, jadi jangan kecewakan semua orang!
“Kamu yang menulis lagu ini?” tanya seorang cowok berbadan kekar dan berkaos merah sembari menghampiriku.
“Judulnya...Goodbye Days?”
“Iya,” jawabku.
Cowok itu mengamat-amati sebuah kertas yang berisikan partitur laguku, kemudian ia lantas berkomentar, “Lagumu bagus.”
“Benarkah?” aku berseru kegirangan. “Terima kasih!”
Cowok itu mengangguk kecil, lalu beralih ke anggota band yang lain. “Kalau begitu, mari kita lakukan,” serunya. Kalimat cowok itu juga sekaligus menjadi pertanda bagiku untuk bersiap-siap memulai rekaman. Aku lantas mendekati mikrofon berpenyaring nafas yang berada di tengah-tengah ruangan. Kuhembaskan nafas panjang sejenak, setelah itu, aku mengenakan headset yang tersambung dengan kolaborasi instrumen band yang tengah memainkan bagian pembuka lagu. Ini dia, Kaoru; dari titik ini, semuanya akan bermula. Aku menarik nafas sekali lagi, dan setelah itu mulai melepaskan suaraku.
***
Satu bulan sudah berlalu sejak aku menyambangi perusahaan rekaman itu, dan hingga saat ini, aku belum menerima satu pemberitahuan pun mengenai CD debutku. Hal itu sebenarnya wajar kalau mengingat ada puluhan—bahkan ratusan—lagu lain yang mengantre untuk dijadikan CD. Bukan, aku bukannya tidak sabaran karena ingin cepat-cepat melihat CD-ku dilepas di pasaran. Aku hanya ingin melihatnya sebelum aku pergi. Ya, selepas kunjunganku ke perusahaan rekaman sebulan silam, perlahan tapi pasti kondisiku semakin memburuk. Dokterku berkata kalau ia tengah mengusahakan yang terbaik agar aku bisa tetap beraktivitas sebagaimana biasanya, tapi aku hanya menanggapinya dengan tersenyum. Dibandingkan dengan dokterku yang notabenenya merupakan orang lain, aku tentu saja jauh lebih mengenal diriku sendiri. Dan aku merasa kalau waktuku sudah semakin dekat.
Pada suatu hari, Kouji memberitahuku kalau sebuah perusahaan pembuat alat-alat selancar kecil telah setuju untuk menjalin kerja sama dengannya setelah ia memenangi sebuah lomba selancar lokal. Dia berkata di telepon kalau perusahaan itu akan menjadi sponsor uji cobanya selama satu tahun ke depan. Selain itu, ia juga berkata kalau ia sekarang telah memiliki sebuah baju selancar keren dari sponsornya itu. Kukatakan kalau aku mau melihatnya mengenakan baju itu, jadi ia menjanjikanku akan datang pada suatu malam sambil membawanya. Namun, aku tidak ingin melihat Kouji hanya memakai baju itu di rumahku; aku ingin melihat ia memakai baju itu di atas ombak. Itulah sebabnya, pada suatu siang, aku memutuskan untuk memakai baju pelindungku dan meminta Okaasan dan Otousan untuk membawaku ke pantai. Pada awalnya, mereka sempat kaget dengan permintaanku itu, tapi setelah aku berkata kalau ini mungkin menjadi kesempatan terakhirku melihat Kouji beraksi di atas papan selancarnya, mereka akhirnya setuju.
Jadi di sinilah aku dengan baju antimatahariku, terduduk di atas kursi roda yang diletakkan di atas pasir pantai.
Okaasan dan Otousan menungguiku di belakang kursi roda, sementara aku memperhatikan Kouji berselancar dengan pakaian khusus selancar barunya. Namun, aku tidak hanya memperhatikan Kouji. Aku hampir tidak pernah berada di luar pada siang hari, jadi aku menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mengamati suasana siang hari. Aku ingin dapat merasakan siang hari dengan mata kepalaku sendiri, bukan hanya sekadar dari video Misaki. Aku ingin dapat melihat laut di siang hari. Aku ingin dapat melihat awan di siang hari. Dan aku ingin dapat melihat matahari di siang hari. Melalui plastik pelinding wajahku, aku mendongakkan kepalaku ke arah lingkaran besar bercahaya yang selama ini kuanggap musuh itu. Sudah terlalu lama aku menghindari matahari, dan kupikir, ini kesempatan yang tepat untuk menyapanya.....
“Akh!”
Seruan Kouji dari tengah ombak membuatku kembali mengalihkan perhatianku kepadanya. Ia sepertinya terpeleset ketika hendak berdiri di atas papan selancarnya, dan akibatnya, ia terjatuh ke dalam air. Tidak butuh waktu lama hingga kepala Kouji kembali menyembul dari air, dan karena Kouji melambaikan tangannya kepadaku sebagai tanda bahwa ia baik-baik saja, aku lantas membalas lambaian tangannya pula.
Tiba-tiba, aku mulai merasakan kegerahan menyergapku. Baju ini memang terasa sedikit tidak nyaman ketika dipakai, tapi berkat tiga buah kipas yang berada di punggung, setidaknya aku menjadi tidak kepanasan. Namun, entah kenapa aku merasa sebaliknya. Aku lantas mengibar-ngibarkan bagian depan bajuku untuk menghasilkan sebuah angin, yang tentu saja memancaing perhatian Okaasan dan Otousan.
“Kenapa?” tanya Otousan kepadaku.
“Aku merasa sedikit kepanasan,” jawabku.
Okaasan langsung berdiri menghampiriku. “Apakah kipasnya bekerja?” tanyanya sambil mengecek bagian ventilasi bajuku. Ia melakukan sesuatu pada kipas itu, dan sebentar kemudian, rasa panas itu mulai menghilang. Tampaknya kipasnya memang tersendat.
“Kalau kamu merasa tidak nyaman dengan baju itu,” ucap Otousan, “lebih baik dilepaskan saja.”
“Apa?” tanyaku dan Okaasan hampir berbarengan. Kenapa Otousan berkata seperti itu?
“Lepaskan saja, lepaskan,” lanjut Otousan. “Kalau kamu melepasnya, kamu tidak akan merasa kepansan lagi. Kamu juga bisa berlari dengan bebas.”
Aku terdiam sejenak mendengar kalimat Otousan yang kurasa ganjil itu. Aku tidak tahu mengapa Otousan mengatakan hal semacam itu—dan aku juga tidak peduli—tapi aku kemudian menanggapinya dengan menggeleng. “Tidak,” balasku. “Kalau aku melakukan itu, maka aku pasti mati,” aku melanjutkan. Pada awal-awal masa remajaku, aku memang sering berpikir kalau hidupku ini tak berarti, dan terkadang merasa lebih untuk mati. Namun itu dulu, sebelum aku mengenal gitar. Semenjak itu, aku merasa memperoleh arti baru dalam hidupku, dan bahkan harapan dan impian baru. Lebih-lebih setelah aku bertemu Kouji, aku dengan segera melupakan keinginan masa laluku itu. “Aku...aku telah memutuskan untuk terus menjalani hidupku hingga aku mati,” ujarku. “Sebab, aku ingin mempertahankan hidup ini dengan segala hal yang aku bisa.”
Otousan langsung melihatku begitu aku selesai mengucapkan kata terakhir. Begitu pula Okaasan, pandangannya dengan segera langsung tertuju ke arahku.“Itu benar,” komentar Okaasan. Aku dapat melihat sebuah senyuman kecil terkembang di wajahnya. “Okaasan tidak tahu kenapa, tapi Otousan menjadi bodoh.”
“Benar,” imbuh Otousan kepadaku. Ia tampak menyesal sendiri setelah melontarkan pernyataan seperti itu. Tentu saja, kalau aku benar-benar melakukan apa yang ia utarakan, maka Otousan pasti akan menyesal seumur hidup! “Maafkan Otousan....”
Sesaat setelah Otousan meminta maaf, aku melihat Kouji sudah keluar dari laut dan kini tengah berjalan ke arahku. Aku lantas beringsut dari kursi roda supaya dapat menghampirinya. Okaasan dengan sigap membantuku, dan dalam waktu sebentar saja, aku sudah melangkahkan kakiku menuju Kouji. Kouji sendiri menatapku dengan pandangan khawatir saat aku berjalan dengan tertatih-tatih ke arahnya.
“Oh,” seruku. Aku tersandung ketika melangkah, dan Kouji dengan sigap langsung menjatuhkan papannya untuk menangkapku sebelum terjatuh. Namun, aku tidaklah terjatuh karena yang kulakukan hanyalah pura-pura tersandung. Aku hanya ingin melihat reaksi Kouji saja. “Bagaimana? Aku datang, kan?” sambil meunduk, aku bertanya kepada Kouji yang kini tengah bersiap menagkapku. Menyadari kalau aku hanya berpura-pura, ekspresi Kouji langsung berubah menjadi aneh. Is seperti kaget dengan gerakanku barusan dan sekaligus lega karena aku tidak jadi jatuh. Aku tersenyum lebar melihatnya. Kuulurkan tangan kananku untuk mencubit pipi Kouji, dan sambil menertawainya, aku lantas berkata, “Wajah yang aneh!”
Tag :// Articles,
Tag :// YUI
Bab 7
Hari Esok Tiada yang Tahu
Kejadian pada malam itu telah membuatku menjadi semakin dekat dengan Kouji. Ia sendiri selalu datang ke rumahku setiap malam sesuai janjinya. Kalau ia sudah datang, kami biasanya akan melakukan banyak hal menyenangkan bersama. Pernah suatu ketika ia berkata ingin mencoba memainkan gitarku. Aku sendiri sebenarnya tidak yakin kalau Kouji bisa memainkan gitar, tapi meskipun begitu, aku tetap menyerahkan gitarku. Benar saja, begitu ia mulai bemain, terdengar bunyi fals yang membuatku ingin menutup kuping. Kami berdua lantas tertawa bersama sesudahnya.
Aku memang menikmati malam-malamku bersama Kouji, tapi aku juga harus ingat kalau ada tawaran rekaman yang masih harus kukejar. Itulah sebabnya aku sekarang hampir tak pernah keluar setelah makan malam dan lebih banyak mengurung diri di kamar untuk berlatih. Seperti malam ini. Aku kembali memegang gitarku dan bersiap untuk memainkannya sementara Misaki—yang mampir kemari untuk menginap—tidur-tiduran di kasurku sambil membaca sesuatu. Sepupuku itu masih libur musim panas, ingat?
Begitu aku mulai menggenjreng gitarku, alunan akustik yang merdu dan suara dengunganku mulai terdengar memenuhi kamar. Sengaja kupilih bagian terakhir laguku karena pada bagian itulah yang belum begitu kukuasai. Aku terus memainkan bagian itu sambil menikmati suaranya ketika tiba-tiba saja jari tangan kiriku yang kugunakan untuk membentuk akord gitar melemah dan terlepas dari senar, membuat permainanku menjadi terhenti sejenak. Kuulangi genjrenganku sekali lagi, dan untuk yang kedua kalinya, jariku terlepas lagi. Entahlah, sepertinya ada sesuatu yang salah. Jari-jariku terasa kaku dan tak bisa kugerakkan sesuai keinginanku. Aku memandangi jari-jari itu sejenak sebelum akhirnya terkaget karena tiba-tiba saja Misaki bertanya mengapa aku berhenti.
“Sepertinya aku agak capek,” jawabku sambil beringsut dari lantai. “Aku akan mengambil makanan,” lanjutku. Aku kemudian keluar dari kamar dan lalu berjalan menuruni tangga ke arah cermin yang tergantung di ruang keluarga. Sekali lagi, aku mengamati jari-jari tangan kiriku. Jari-jari itu kukepalkan dan kulepas berulang-ulang, hingga setelah aku mantap kalau kekuatan genggamanku sama seperti biasanya, aku mengangguk dan lantas beranjak ke kulkas untuk mengambil makanan. Tak apa, Kaoru, tak ada yang salah. Kamu hanya kecapekan saja karena harus mempersiapkan rekaman pertamamu, itu saja.
Setelah mengambil sesisir pisang, dua mangkuk puding, dan dua kaleng manisan, aku kemudian kembali naik ke kamar. Misaki langsung menyambutku dengan gembira saat melihatku membawakan panganan-panganan itu, dan sesaat setelah aku meletakan kesemuanya di meja, ia dengan segera menyahut semangkuk puding. Aku sendiri lebih memilih untuk melanjutkan memainkan gitarku untuk memastikan kalau tangan kiriku baik-baik saja. Satu genjrengan. Dua genjrengan. Sebuah intro. Hei, sepertinya jari-jariku memang berfungsi seperti biasa....
PANG!
Lagi-lagi...! Untuk ketiga kalinya, jari tangan kiriku kembali tidak dapat kugerakkan. Perlahan, kuamati tangan kiriku. Benar, tangan itu terasa seperti mati rasa. Tak peduli bagaimana aku menggerakkan jari telunjuk, jempol, atau kelingkingku, tidak ada yang berubah—semuanya masih tetap diam. Namun, aku mencoba untuk tidak berputus asa, jadi aku lantas memulai untuk memainkan gitarku sekali lagi. Kuangkat tangan kananku untuk mulai memetik senar gitar, dan....
PANG!
Apa ini?
Tadi jari-jari tangan kiriku yang tak bisa kugerakkan, sekarang kenapa jari-jari tangan kananku yang jadi begini? Jemari yang biasanya lincah memainkan senar nilon itu kini tidak bisa lagi kuarahkan. Aku kembali mencoba untuk memetik gitarku sebagaimana biasanya, tapi yang terdengar justru suara petikan yang keras dan sumbang. Bagaimana mungkin? Ini bukanlah permainan gitarku. Aku tetap tidak bisa menerima kalau performance-ku menjadi berantakan begini, jadi aku menggenjreng lagi sambil berharap jariku akan lentur kembali dengan sendirinya. Namun, hasilnya tetap sama, bahkan menjadi lebih parah. Aku lalu menggenjreng sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Berulang-ulang, senar gitar itu kupetik tanpa jeda, menghasilkan suara cempreng yang berkelanjutan. Meskipun begitu, jariku tetap saja terkejur dan tidak bisa menghasilkan suara yang merdu seperti biasanya.
Apa ini?
Kenapa...kenapa aku tidak bisa menggerakkan jari-jariku?
***
Otousan langsung membawaku dan Okaasan menemui dokterku begitu aku menyampaikan keluhanku. Ia titip rumah kepada Misaki, dan tidak lama kemudian, kami sudah berada di dalam mobil yang menuju ke rumah sakit. Padahal, sekarang sudah lumayan larut, sekitar jam sembilan malam. Untunglah, dokterku kebetulan tengah ada di rumah sakit dan belum pulang. Atas saran dokterku, aku lalu setuju untuk melakukan CAT-scan, dan kira-kira satu jam kemudian, dokterku lantas memanggil kami bertiga untuk membeberkan diagnosisnya.
“Meskipun untuk saat ini tingkatnya tidak begitu parah, tapi otaknya tengah mengalami kemunduran,” kata dokterku kepada Otousan. Ia memperlihatkan hasil CAT-scan sekali lagi, kemudian melanjutkan, “Saya bisa bilang kalau gejala pelemahan syaraf yang disebabkan oleh XP sudah mulai tampak.”
Sambil berbaring di ruang praktik, aku menguping pembicaraan keduanya. Pelemahan syaraf? Apa itu berarti aku tidak bisa bermain gitar lagi? Aku menengok sejenak ke arah Okaasan, dan tanpa kuminta, ia langsung menggamit tanganku untuk membuatku sedikit lebih tenang.
“Untuk ke depannya,” kata doketerku lagi, “tubuhnya akan menjadi kaku. Kemudian...,” ia menggantung kalimatnya.
“Maksud Sensei, dia akan meninggal?”
Apa?
Apa itu benar?
Aku, sekali lagi, mengerling ke arah Okaasan. Dapat kurasakan genggaman tangannya menguat, seakan-akan ia ingin mengalirkan lebih banyak kekuatan kepadaku. Otousan sendiri dengan kasar bangkit dari kursi dan lalu berjalan meninggalkan ruangan praktik. Dokterku menyusul tak lama kemudian, dan karena aku ingin tahu apa yang terjadi, aku mengajak Okaasan untuk melihat keduanya dari kejauhan.
Otousan ternyata berhenti di lobi rumah sakit. Ia duduk di situ sendirian sementara dokterku beranjak mendekatinya. Selama beberapa saat, tidak ada percakapan di antara mereka, sampai akhirnya lamat-lamat aku mulai mendengar Otousan berbicara. “Tapi bukankah ini aneh, Sensei?” tanyanya. “Aku tidak pernah membiarkannya terkena sinar matahari.” Ia menghela nafas sejenak. “Ketika ia kecil, ia selalu merengek ingin pergi ke luar,” kata Otousan menambahkan, “dan tak peduli dia menangis atau beteriak, aku akan menamparnya dan tetap menguncinya di dalam rumah.”
Ah, ya. Aku ingat. Waktu masih kecil, aku memang seringkali hanya dapat melihat teman-teman sebayaku bermain petak umpet di musim panas. Tentu saja aku juga ingin bergabung bersama mereka, tapi Otousan selalu melarangku keluar, dan bahkan memukulku di wajah. Kala itu aku tidak tahu alasan Otousan melakukannya. Namun, semakin aku beranjak remaja, aku jadi semakin paham kenapa.
“Tapi mengapa,” tiba-tiba, Otousan kembali berbicara, “mengapa semuanya jadi begini?” Perlahan, kudengar nada bicara Otousan berubah. Dari yang tadinya hanya lamat-lamat menjadi semakin keras. “Aku melakukan semua yang kubisa untuk melindunginya,” ujar Otousan. Sekarang suara tangis mulai terdengar di antara kata-katanya. “Apa itu artinya semuanya itu sia-sia? Dan kenapa, Sensei,” ujarnya kepada dokterku, “kenapa putriku harus mengalami hal semacam ini?”
Aku mengamati saat Otousan terisak dan dokterku menenangkan dirinya. Tanpa kusadari, tiba-tiba saja air mataku pun ikut meleleh. Selama ini, seburuk apa pun kondisiku, Otousan tidak pernah menitikkan air mata di hadapanku. Ia paling-paling hanya merespons sejenak dan kemudian membawaku ke rumah sakit kalau memang dirasanya perlu.
Sekarang, ia menangis.
Rasanya, baru kali ini aku benar-benar merasakan betapa Otousan menyayangiku. Aku seringkali menganggap ia tidak pedulian terhadap diriku, dan itu sebabnya aku kadangkala tidak segan untuk menyentaknya. Namun, sekarang aku sadar kalau ternyata Otousan amat menyayangiku.
Untuk kedua kalinya, aku kembali merasakan air mata mengalir membasahi pipiku.
***
Kouji kembali berkunjung ke rumaku keesokan malamnya, seperti biasa. Namun, kali ini ia tidak datang untuk melakukan suatu hal yang konyol bersamaku seperti malam-malam sebelumnya. Ia datang untuk membesukku. Misaki sempat menelepon tadi sore dan memberi tahu Kouji mengenai keadaanku yang sekarang, jadi aku tidak perlu bercerita panjang lebar mengenai hal itu. Ah, selalu saja begitu. Selalu saja ia yang menginformasikan segala hal tentang penyakitku kepada Kouji. Sudahlah, setidaknya aku jadi tidak usah repot-repot.
Aku tengah tidur-tiduran di atas kasur ketika kudengar Kouji memanggil namaku. Cepat- cepat kuubah posisiku menjadi duduk bersadar di dinding. Masa’ aku menyambut Kouji dengan telentang? Tidak sopan!
“Aku masuk, ya,” kata Kouji. Tak lama kemudian, aku melihat sosoknya berjalan melewati pintu geser kamarku. Pintu itu memang kubiarkan terbuka supaya aku dapat mendengar Okaasan memanggil atau, jika aku butuh bantuan seseorang, maka aku dapat dengan mudah memanggilnya. Kami saling berpandangan selama beberapa saat sebelum akhirnya Kouji berkata kepadaku, “Bagaimana keadaanmu?”
Sebagai jawaban, aku terdiam. Kepalaku sedikit kuarahkan ke tangan kiriku, tanda aku masih kesulitan menggerakkkannya. Kouji sendiri sepertinya langsung paham dengan gerakanku barusan sehingga ia tidak bertanya lagi. Harus kuakui, tindakan Misaki tadi siang sedikit banyak sudah membantuku.
“Maaf, ya,” ujarku tiba-tiba.
Ekspresi Kouji langsung berubah menjadi heran setelah mendengar kata-kataku itu. “Apa?” tanyanya.
“Meskipun kamu sudah bekerja paruh-waktu...,” jawabku lirih, “pada akhirnya, aku tidak bisa menyanyi lagi.” Aku menunduk semakin dalam sementara Kouji menatapiku. “Maafkan aku.”
Alih-alih menanggapi, Kouji justru berjalan menjauh. Ia melangkahkan kakinya menuju jendela kamar yang dulu sering kugunakan untuk memperhatikannya di halte bus, lalu setelah melongok ke luar sejenak, ia bertanya padaku, “Aku tidak melakukan sesuatu yang aneh, kan?”
“Hah?”
“Kamu kan biasa melihatku dari sini,” jawab Kouji seraya menunjuk jendela itu.
Aku bangkit dari sandaranku, kemudian beringsut ke sisi tempat tidur. “Hal aneh seperti yang kamu maksud?” tanyaku.
“Misalnya aku mengupil....”
“Tidak kok,” jawabku sambil tertawa kecil. Ada-ada saja.
“Kalau suara-suara yang aneh?”
“Tidak.”
Mendengar jawabanku, Kouji terlihat lega. “Yang betul? Senang mendengarnya kalau begitu.”
Aku lantas bangkit dari kasur dan berjalan ke arah Kouji—yang sekaligus juga ke arah jendela itu. Kulongokkan kepala sejenak untuk mengintip ke luar. Gelap. Hanya cahaya lampu rumah jalanan yang bisa kulihat, atau cahaya mesin penjual otomatis di halte bus. Aku menatap halte bus itu selama beberapa saat sebelum akhirnya berpaling ke arah Kouji. “Pertama kali aku melihatmu,” aku memulai percakapan, “aku melihat Kouji yang seperti anak-anak,” lanjutku. Aku langsung menyadari kalau Kouji menatapku dengan tatapan memohon dan aku tahu kalau ia ingin aku menceritakan apa maksud dari pernyataanku barusan. Aku tersenyum kecil, setelah itu mulai bertutur.
Waktu itu, aku masih empat belas tahun—sekitar kelas 2 SMP. Sudah menjadi kebiasaanku untuk duduk-duduk di samping jendela sebelum matahari terbit (dan masih berlanjut sekarang) sambil melihat ke jalanan di depan halte bus. Pada suatu pagi, aku melihat ada seorang cowok menghentikan skuternya di dekat halte itu—Kouji. Cowok itu mengenakan rompi, kemeja putih, dan celana hitam sambil menenteng tas, jadi aku tahu kalau dia hendak berangkat sekolah. Ia lantas turun dari skuter dan lalu berjalan mendekati sebuah papan seluncur. Diamat-amatinya papan seluncur itu dan dielus-elusnya, seakan-akan ia kagum betul dengan benda itu. Tak cukup dengan itu, ia juga membaringkan papan seluncur itu di tanah. Ia kemudian berpose seakan-akan tengah berselancar di atas ombak. Ketika ia hendak menaiki papan itu, seorang pria berotot dan bertelanjang dada keluar dari sebuah toko. Pria itu lantas menegurnya karena telah bermain-main dengan papan miliknya, dan aku melihat cowok itu langsung bertubi-tubi minta maaf. Aku tertawa sendiri melihat kejadian itu.
Beberapa hari kemudian, aku kembali melihat cowok itu. Kali ini, ia tidak sendirian. Ada dua orang lain bersamanya, dan kulihat ia tengah memamerkan papan seluncur yang baru dibelinya. Aku tersenyum melihat ketiganya bercanda, lebih-lebih ketika ia lantas memelorotkan celana sehingga celana pendeknya terlihat. Waktu itu aku sadikit terkejut juga. Namun, keterkejutanku berubah menjadi sebuah tawa saat melihatnya terjatuh karena tersandung celananya sendiri.
“Pada waktu itu kamu terlihat bahagia,” aku mengakhiri ceritaku sambil sekali lagi memandang ke arah halte bus di bawah. “Melihatmu seperti itu, aku juga turut bahagia.”
“Ah, kamu melihatnya,” kata Kouji seraya tersenyum malu.
“Aku juga seperti itu, kok.”
“Heh?”
“Waktu pertama kali mendapat gitar,” terangku, “aku juga gembira seperti kamu.”
“Begitu, yah...,” gumam Kouji perlahan.
Setelah itu, intensitas percakapan kami langsung berkurang drastis. Kouji lebih banyak diam, dan begitu pula aku. Yang kami bicarakan paling-paling hanya hal-hal tak penting seperti bagaimana Kouji menghabiskan liburannya atau apakah aku sudah membuat lagu baru lagi akhir-akhir ini. Namun, kami sama sekali tidak membicarakan keadaanku. Tidak sedetik pun.
Setelah Kouji menghabiskan waktu bersamaku dengan kekakuan yang amat terasa, ia lantas beranjak untuk pamit. Aku mengantarkan Kouji keluar rumah dan bahkan ketika ia mulai menuruni tangga beranda rumahku, aku masih memandanginya. Ia sempat menoleh ke arahku sejenak ketika hendak berlalu, sedangkan aku hanya membalas dengan senyuman kecil.
“Hei!” seruku ketika Kouji sudah hampir berada di bawah. “Meskipun tanganku seperti ini, kamu bisa mendengar suaraku, kan?”
Kouji terdiam. Ia menatap ke arahku selama beberapa saat tanpa suara.
“Kamu bisa mendengarnya, kan?” aku mengulangi pertanyaanku.
“Ya, aku bisa mendengarnya,” balas Kouji dari bawah sana.
Aku tersenyum sejenak mendengar jawaban Kouji. “Kalau begitu, aku akan bernyanyi,” aku melanjutkan. Benar. Meskipun aku tidak dapat bermain gitar lagi, tapi setidaknya aku masih dapat menggunakan suaraku untuk bernyanyi, kan? Itu berarti aku masih mungkin pergi ke perusahaan rekaman dan membuat CD debutku. Setidaknya, usaha Kouji bekerja paruh-waktu tidak akan sia-sia. “Sampai besok kalau begitu!” seruku sembari melambaikan tangan kepada Kouji.Aku kemudian berlari naik menuju rumah. Sebelum masuk, aku sempat melihat ke bawah, ke arah Kouji yang kini tengah berjalan menjauh. Di antara lampu jalanan, sepintas aku melihat bahu Kouji naik turun. Kouji...masa’ sih dia menangis?
bersambung ke bab 8
***
Tag :// Articles,
Tag :// YUI
6
Awal dari Sebuah Akhir
Semenjak kedatangan Kouji ke rumah tempo hari, aku seakan jadi kehilangan motivasi untuk melakukan segala hal. Nafsu makanku turun drastis, dan pemandangan halte bus yang dulu selalu membuatku tersenyum kini justru menjadi penyayat hatiku. Tidak ada lagi berjalan keluar setelah makan malam dan bernyanyi di depan statsiun dengan ditemani petikan gitar dan sebatang lilin. Aku kini lebih banyak menghabiskan waktu di kamarku ketika malam tiba—entah hanya menyenandungkan lagu ciptaanku atau melakukan hal lain yang bisa kulakukan. Seperti saat ini, sambil tidur-tiduran, aku menggumamkan laguku.
♪ Dakara ima ai ni yuku sou kimetanda
Pocket no kono kyoku wo kimi ni kikasetai
Sotto volume wo agete tashikamete mita yo... ♪
“Kaoru, makan malam!”
Itu suara Okaasan. Sudah waktunya makan malam lagi, ya? Aku paling-paling hanya akan makan sedikit seperti biasa, dan setelah itu, aku akan kembali ke kamar untuk melakukan sesuatu sampai akhirnya terlelap. Dengan perlahan, aku lalu menyusuri tangga menuju ruang keluarga yang menjadi satu dengan ruang makan. Kulihat Misaki tengah duduk di salah satu kursinya, dan begitu dia melihatku, dia menyapa dengan sapaan ‘Osh’-nya yang biasa. Sepupuku itu memang terkadang menumpang makan di sini, jadi bukan hal yang aneh kalau ia tiba-tiba saja muncul di meja makan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Otousan sendiri kini mendapat giliran memasak, dan berhubung ia juga menjadi koki di restorannya, aku tahu kalau kali ini kami akan makan enak. Semuanya terlihat biasa saja, dan itu sebabnya aku beranjak menuju kursi makan seperti yang biasa kulakukan. Namun, tiba-tiba saja....
“Kalau mangkuk ini bisa, kan?”
Deg! Suara Kouji! Tapi bagaimana.... Dengan segera, aku menengok ke arah sumber suara tersebut yang berada tepat di belakangku. Dan di sanalah ia, mengenakan baju polo garis-garis hijau-hitam sambil membawa setumpuk mangkuk dengan kedua tangannya. Fujishiro Kouji kini berdiri tepat di depanku!
“Yo,” sapa Kouji perlahan sambil menganggukkan kepalanya sedikit. Selama beberapa saat, aku terpana saat melihatnya berada di dalam rumahku. Kemudian, baru kusadari kalau aku hanya mengenakan piyama berlengan panjang dan celana training yang kugunakan untuk tidur seharian tadi. Itulah sebabnya aku buru-buru naik ke atas untuk mengganti baju. Aku turun sekitar sepuluh menit kemudian setelah mengganti piyamaku dengan kemeja berwarna pink dan celana jins biru tua. Setidaknya, penampilanku kini tidak seperti orang yang baru saja bangun tidur.
Piring-piring dengan hidangannya sudah tertata rapi dan semua orang—termasuk Kouji—sudah duduk mengelilingi meja makan ketika aku menghampiri mereka. Kurapikan rambut panjangku yang belum sempat kusisir secara sempurna di atas, kemudian aku mengambil tempat duduk di satu-satuya kursi yang tersedia.
“Itadakimasu,” ujarku setelah tidak ada yang bersuara selama beberapa saat. Melihatku berbicara seperti itu, Misaki langsung menyusul, dilanjutkan kemudian oleh Okaasan, Kouji, dan terakhir, Otousan. Aku hanya melihat saja saat Okaasan mulai menyendokkan salad ke piring Otousan dan piringku. Begitu pula saat Misaki berbicara kepada Otousan dengan mulut penuh udang goreng sehingga tidak ada satu orang pun yang mengerti apa yang dia bicarakan.
“Silakan, Fuji-kun, makanlah sepuasmu,” kata Okaasan menawarkan.
“Ah, terima kasih,” balas Kouji. “Semuanya terlihat enak sekali!”
“Kamu itu anak yang baik, ya,” Otousan ikut menimpali.
“Bagaimana mungkin?” balas Kouji.
“Benar, kok. Sepertinya kamu menyenangkan,” ujar Otousan.
“Ini, makanlah,” katanya lagi.
Apa ini?
Semua percakapan dan gerakan-gerakan ini seperti sudah diatur saja. Bagaimana mungkin Misaki dan Kouji bisa terlihat akrab begitu padahal sebelumnya mereka bertengkar hebat? Juga, mana mungkin Otousan menawarkan makanan kepada Kouji? “Ini aneh,” kataku pada akhirnya, “benar-benar aneh. Siapa yang memikirkan ini semua?”
“Ayahmu yang mengundangku ke sini,” jawab Kouji.
“Otousan!” seruku terkaget. “Apa yang Otousan bilang kepada Kouji?” tanyaku penuh selidik.
“Jangan marah dulu,” Kouji buru-buru menengahi.
“Tidak, aku tidak marah, kok,” jawabku. Aku lantas mengedarkan pandanganku ke semua orang yang ada di meja makan, dan ketika mataku berhenti di tempat Kouji duduk, aku lantas bertanya kepadanya, “Ada apa?” tanyaku. “Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?”
Kouji tidak langsung menjawab, tapi ia kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arahku. “Aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu,” ujarnya sambil merogoh saku celananya. Ia lalu mengeluarkan sebuah kertas dari sana.
“Nih,” katanya sembari menyodorkan kertas itu kepadaku.
Aku meraih kertas yang ada di hadapanku, kemudian membacanya dengan lebih teliti. Sebuah brosur agaknya. Tulisan besar-besar berwarna merah yang merupakan campuran huruf hiragana, katakana, dan romanji itu sontak menarik perhatianku. Bukan, bukan bentuk hurufnya atau ukurannya yang membuatku tertarik, melainkan isinya. Tulisan dalam brosur itu berbunyi:
(APAKAH KAMU INGIN MEMASUKKAN LAGU ASLIMU KE DALAM CD?)
Ini...sebuah tawaran untuk rekaman! Aku sering mendengar kalau beberapa perusahaan musik memang memberikan kesempatan bagi penulis lagu pemula untuk menelurkan CD album mereka sendiri, tapi aku belum pernah sekali pun mencoba untuk ikut serta. Aku sudah cukup sadar diri dengan penyakitku, jadi yang kulakukan hanyalah bermimpi untuk ikut masuk ke dapur rekaman. Namun, lihat apa yang Kouji bawakan untukku kini. Bukankah itu berarti ia memintaku untuk terus berusaha mewujukan impianku?
“Bagaimanapun juga,” ujar Kouji, “aku ingin mendengar suaramu sekali lagi.” Ia kemudian menggaruk-garukkan tangan kanannya di rambut. “Tapi karena aku tidak begitu cerdas, maka hanya cara inilah yang bisa kupikirkan.”
Aku memandangi brosur tersebut. Mataku mulai menjelajahi detail informasi yang tertulis di sana. Saat membaca berapa biaya pendaftaran yang harus kubayar, nafasku langsung tertahan. Bayangkan, 200.000 yen supaya laguku dapat dijadikan CD! Mahal sekali! Tentu saja; kalau kamu memperoleh sesuatu, maka kamu harus mengorbankan sesuatu pula.
“Aku mulai bekerja paruh-waktu supaya bisa membayarnya,” ungkap Kouji, “tapi, sepertinya tabunganku belum cukup.”
Apa? Dia bahkan akan membayari biayanya dengan hasil kerja paruh-waktu? Coba lihat berapa uang yang harus dikeluarkan: 200.000 yen! Jumlah itu pastilah amat besar bagi Kouji yang merupakan pelajar SMA. Maksudnya, berapa sih, upah untuk kerja paruh-waktu? Paling-paling tidak sampai 10.000 yen. Kalau dia memang benar-benar mau membayari biaya pendaftaran itu, dia harus bekerja ekstrakeras, bahkan mungkin melakukan penghematan besar-besaran.
Dan ia melakukan semua hal itu supaya aku dapat merilis CD-ku?
Kini, aku tahu kalau aku adalah seseorang yang sangat spesial di mata Kouji. Ia tidak mundur setelah tahu keadaanku yang sesungguhnya dari Misaki. Sebaliknya, ia justru berusaha sekuat tenaga untuk membantuku.
“Kalau masalah uang, sih,” sela Otousan, “jangan khawatir, aku yang akan membayar.”
“Benarkah?” balas Kouji girang yang diamini oleh Otousan. “Tapi, sepertinya akan lebih baik kalau aku sendiri saja,” lanjutnya.
“Kenapa?” tanya Otousan.
“Itu keputusanku,” Kouji menjawab sembari memandang ke arah Otousan. “Ini sesuatu yang kumulai, jadi aku ingin menuntaskannya hingga selesai.”
“Ya sudah kalau begitu.”
Setelah selesai berbincang dengan Otousan, Kouji lantas beralih kepadaku yang masih terpana dengan kata-katanya yang penuh tanggung jawab itu. Perlahan-lahan, rasa benciku kepadanya mulai mencair, dan bahkan berubah menjadi rasa kagum. “Jadi bagaimana?” tanyanya meminta persetujuanku. “Tidakkah kamu ingin memasukkannya ke CD? Lagumu itu....”
Aku terdiam. Bukankah belum lama ini aku telah memutuskan untuk membuang impianku dan tidak bernyanyi lagi? Namun, di sisi lain, aku juga sudah lama sekali memendam keinginan untuk membuat album CD-ku sendiri. Lagipula Kouji juga sudah berusaha keras untuk membayari uang pendaftaran yang jumlahnya tidak sedikit itu. Karena itulah, sambil berusaha menahan tangis terharu, aku lantas melihat ke arah Kouji dan mengangguk mantap. Ini mungkin akan menjadi kesempatanku sekali seumur hidup, jadi apa salahnya membangun kembali mimpi yang sudah kuhancurkan dan memulainya dari awal?
“Aku berhasil...,” gumam Kouji perlahan.
***
Seusai makan malam, Kouji mengajakku untuk keluar berjalan-jalan. Aku melangkah lebih dulu, sementara Kouji menyusul di belakang. Sudah agak lama juga sejak kami berjalan bersama malam-malam begini. Terakhir kali adalah waktu di Yokohama itu, ingat? Sekarang, kami kembali berduaan layaknya sepasang kekasih—dan memang itu yang sebenarnya kuinginkan! “Aku tak menyangka kamu akan berbuat sejauh ini untukku,” aku memulai pembicaraan.
“Tidak mengapa.”
“Terima kasih, ya,” kataku. Kouji hanya membalas dengan terkekeh. “Aku ingin tahu, bisakah orang sepertiku...,” lanjutku sambil terus berjalan.
“Heh?” seru Kouji dari belakang.
“Rasanya, aku tidak mungkin melakukan hal ini,” aku membalas. “Kalau orang sepertiku...,” sambungku. Aku kemudian berjalan melintasi rel tempat kami pertama kali bertemu. Untuk beberapa saat, aku terus melangkah, tapi aku kemudian berhenti saat tak kudengar langkah Kouji mengikutiku. Benar saja; dia berhenti tepat di seberang rel. “Kenapa? Apa aku salah bicara?” tanyaku kepadanya.
Kouji tidak mengiyakan, tidak pula membantah. Alih-alih begitu, dia menjawab dengan jawaban lain. “Aku menyukaimu.”
“Heh?” balasku. Aku memang menginginkan Kouji mengatakan hal itu, tapi tetap saja aku merasa kaget ketika mendengarnya.
“Meskipun keadaanmu seperti ini,” ia membalas dari seberang rel. “Jika malam tiba, mari kita bertemu!” tambahnya.
Aku terdiam menanggapi kata-kata Kouji. Kenapa? Kenapa Kouji berbuat begini untukku? Apakah karena dia menyukaiku?
“Tidurlah ketika siang, dan ketika matahari terbenam...,” Kouji melanjutkan,” aku akan menemuimu.”
Si Bodoh itu.... Dia sudah melakukan banyak hal untukku, dan bahkan ia rela untuk pergi keluar malam-malam hanya sekadar untuk menemuiku? Kenapa...? Aku tidak tahu kata apa yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku kini, dan sebelum aku menemukan kata itu, perlahan-lahan kurasakan dua butir air mulai mengalir dari pipiku. Cepat-cepat kuangkat tangan kananku untuk menyekanya sambil memalingkan wajah. Aku tak ingin Kouji mendapatiku menangis.
“Hei,” panggil Kouji sambil beranjak ke arahku. Aku pun dengan segera menjauh darinya supaya ia tidak bisa melihat bekas air mata di mukaku. “Kenapa? Kamu menangis?” tanya Kouji sambil mengejarku.
“Tidak, aku tidak menangis,” aku menyangkal.
“Kamu menangis, kan?”
“Sudah kubilang aku tidak menagis,” jawabku sambil kembali mengelak darinya.
“Biar kulihat wajahmu,” Kouji berkata sambil sedikit memaksaku. Aku sempat lolos dari tangannya, tapi kemudian, ia berhasil meraihku sekali lagi. “Jangan menangis,” ujarnya berusaha menghiburku. Dipandanginya bola mataku agak lama, dan setelah itu, ia mencubit kedua pipiku seraya berkata, “Ayo, tersenyumlah!”
Aku mengejapkan mataku sekali. Entah mengapa aku justru semakin ingin menangis saat Kouji memintaku untuk tersenyum. Kouji sendiri justru tertawa setelah melihat wajahku.
“Wajah yang aneh,” gumamnya.
Masih dengan perasaan tak karuan, aku hanya bisa menanggapi kata-kata Kouji itu dengan sebuah kata. “Jahat,” balasku. Aku tidak tahu mengapa kata itu yang pertama kali terlintas di benakku; mungkin karena dia justru tertawa saat melihatku menangis. Kouji kembali memandangi wajahku selama beberapa saat sebelum akhirnya melepaskan tangannya dari pipiku dan mulai mendekatkan wajahnya ke wajahku.
Kemudian, kami berciuman.
Di sini, di rel kereta tempat pertama kali kami bertemu, Kouji menempelkan bibirnya di atas bibirku. Darahku serasa berdesir dan perasaan hangat perlahan-lahan mulai menyelimutiku. Ini pertama kalinya aku dicium di bibir oleh seorang cowok, dan rasanya mendebarkan sekaligus menyenangkan! Kamu berciuman agak lama, sekitar satu menit. Kouji lantas dengan lembut melepas ciumannya dari bibirku dan lalu mengulurkan tangannya untuk merengkuhku. Perlahan, air mataku kembali menetes. Selama hidupku, baru kali ini aku tahu bahwa ternyata ada seorang cowok yang benar-benar tulus mencintaiku meskipun ia sudah mengetahui keadaanku yang sesungguhnya. Sekarang, dari saat ini, aku akan mengakhiri semua masa laluku; impianku, hubunganku dengan Kouji, dan segala hal lainnya akan kuhentikan malam ini juga. Sebagai gantinya, aku akan mengganti semua itu dengan sesuatu yang baru—benar-benar baru dan berbeda dengan yang lampau.
Ya, Kouji, Inilah awal dari diriku yang baru!
Tag :// Articles,
Tag :// YUI
“Aku Tidak Akan Menemuinya Lagi...”
Otousan dan Okaasan sepertinya tidak ingin mengambil risiko setelah apa yang terjadi padaku. Setelah Misaki memberi tahu keduanya kalau aku sudah berada di rumah (dan berdasar yang kudengar, ia sempat membentak-bentak Kouji dan membeberkan tentang keadaanku yang sebenarnya), mereka langsung mengantarkanku ke rumah sakit hari itu juga. Kali ini, aku harus mengesampingkan rasa benciku terhadap rumah sakit. Aku masih ingin hidup, dan aku tidak keberatan meskipun harus pergi ke tempat yang sangat tidak kusukai.
Setibanya di rumah sakit, aku langsung mendapatkan pemeriksaan segera dari dokterku. Ia memperhatikan kulit lenganku yang sedikit terkena matahari sambil bertanya berbagai macam hal, meskipun Otousan yang lebih banyak menjawabnya. Akhirnya, setelah memeriksa bagian-bagian tubuhku yang lain, ia sampai pada satu kesimpulan.
“Dia akan baik-baik saja.”
Mendengar dokterku berkata seperti itu, aku langsung merasa lega. Syukurlah kalau begitu. “Dia akan baik-baik saja, Dok?” tanya Otousan tak percaya.
“Kalau tereskpos segini saja, seharusnya tidak jadi masalah,” jawab dokterku.
“Syukurlah kalau begitu,” Okaasan menimpali.
Setelah berbicara dengan kedua orang tuaku, dokter itu lalu beralih kepadaku. “Seharusnya tidak ada efek samping pada wajah dan tubuhmu,” ujar dokterku, “tapi kalau ada, segera beri tahu aku.”
Saat itu, aku hanya bisa mengangguk perlahan menanggapinya. Dibilang baik-baik saja oleh dokterku sudah merupakan suatu hal yang bagus, dan aku tidak berpikir tentang hal lain selain itu.
Setelah selesai dengan pemeriksaanku, Otousan memutuskan untuk menunggu di rumah sakit hingga matahari terbenam sehingga aku dapat pulang dengan aman. Kami banyak terdiam selama perjalanan, sampai aku memecah kesunyian yang tak nyaman ini dengan satu kata. "Apa?"
“Jangan bilang ‘apa’ kepadaku,’” jawab Otousan sambil terus menyetir. “Lagipula, siapa cowok itu? Kenapa kamu tidak pernah bilang-bilang?”
“Aku tidak ingin membicarakan ini,” jawabku singkat.
“Apakah dia orang yang Kaoru sukai?” kali ini Okaasan bertanya kepadaku.
Pertanyaan Okaasan itu langsung menggamparku dengan telak. Jawabanku tentu saja sama dengan pertanyaan Okaasan, hanya saja berupa kalimat pernyataan. Namun, aku tidak menyuarakannya dan tetap memilih menyimpan jawaban itu di pikiranku. Sebagai gantinya, aku justru memalingkan wajahku untuk menatap ke luar jendela.
“Pasti begitu, kan?” tanya Okaasan sekali lagi, berusaha meminta ketegasanku.
“Begitu?” Otousan jadi ikut-ikutan bertanya.
“Memangnya kenapa kalau iya?” balasku dengan ogah-ogahan. Memikirkan kenyataan bahwa Kouji adalah orang yang kusukai sekaligus orang yang hampir saja membunuhku membuat hatiku perih. Namun yang lebih penting lagi, menyadari bahwa hubungan kami yang singkat itu sudah berakhirlah yang paling menyesakkan dadaku. “Tapi semuanya sudah selesai,” tambahku.
“Hah?” sambung Okaasan.
“Meskipun aku berusaha untuk berpikir penyakitku in tidak ada hubungannya dengan aku dan dia,” jawabku tanpa memandang Okaasan, “pada akhirnya, merupakan suatu hal yang mustahil bagiku untuk menyukai seseorang.”
Sepi. Okaasan tidak menanggapi kata-kataku barusan. Lebih-lebih Otousan. Ia tetap melihat ke depan sambil menyetir, seolah-olah aku tidak mengatakan apa pun.
“Jangan khawatir,” lanjutku, “aku tidak akan menemuinya lagi.” Aku menahan kalimatku sejenak.“Kurasa, dia juga tidak ingin punya pacar yang sakit.”
“Jangan bilang seperti itu,” ujar Okaasan menimpali setelah aku selesai dengan kata-kataku.
“Ini bukan tentang penyakit, ini hanya tentang kepribadianmu saja,” Otousan turut menambahkan.
“Tapi dia punya masa depan,” balasku.
“Kamu juga punya masa depan.”
“Benarkah?” kataku dengan nada ketus yang, meskipun begitu, dibalas dengan ucapan mengiyakan dari Otousan. “Cuma kata-kata manis saja,” gumamku.
“Apa kamu bilang?”
“Meskipun aku tidak bisa sembuh?” aku menjawab kata-kata Otousan dengan nada meninggi. Sudah cukup. Mereka sudah banyak menghiburku dengan kata-kata penyemangat; ini saatnya keduanya membiarkan aku menghadapi kepahitan hidup.
“Itu tidak benar,” Otousan buru-buru menanggapi.
“Kalau begitu, lihat mataku ketika mengatakannya!” Untuk kedua kalinya, aku menyentak Otousan. “Aku tidak akan tertipu lagi,” sambungku sambil mengalihkan pandangan ke luar. “Aku tidak akan menjadi anak kecil selamanya.”
Dan begitulah pembicaraan kami dalam mobil malam itu berakhir. Sudah terlalu lama Otousan dan Okaasan selalu mengatakan bahwa penyakitku dapat disembuhkan. Namun, yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah memberikan sebuah harapan palsu. Dulu, aku percaya begitu saja kalau suatu hari kelak aku akan sembuh dan dapat hidup seperti orang normal. Tapi itu dulu, sepuluh tahun yang lalu. Aku sekarang sudah enam belas tahun, dan aku sudah cukup mengerti bahwa hidupku tidak akan pernah sama seperti orang lain. Aku tidak akan dapat menjalani hidup seperti Otousan dan Okaasan. Aku tidak mungkin hidup seperti Misaki. Dan yang lebih penting lagi, kehidupanku ini jelas berbeda dengan kehidupan Kouji. Itulah sebabnya, meskipun berat, aku harus merelakan untuk tidak lagi bertemu Kouji. Menemuinya hanya akan mengingatkanku kalau aku bukanlah “orang yang tepat”. Ia adalah cowok normal yang memiliki masa depan, sedangkan aku? Aku hanyalah seorang cewek sakit! Karena itu, Kaoru, mulai sekarang jangan temui Kouji lagi.
***
Keesokan malamnya, aku tidak pergi ke luar seperti malam-malam biasanya. Aku tahu kalau aku keluar, Kouji pasti akan mendatangiku di depan stasiun. Itulah sebabnya aku lebih memilih untuk langsung naik ke kamarku dan tidur lebih awal saja seusai makan malam.
Pada saat aku masih terlelap di atas kasur, samar-samar aku mendengar bunyi bel pintu rumah yang membuatku terjaga. Selarut ini? Siapa yang kira-kira datang? Aku tidak ingin membangunkan Okaasan dan Otousan, jadi aku bangkit dari tempat tidur dan lalu berjalan turun. “Siapa itu?” seruku kepada seseorang di balik pintu.
“Ini aku.”
Suara itu... suara Kouji! Darahku serasa berhenti mengalir ketika tahu Kouji-lah yang membunyikan bel. Untuk apa dia malam-malam begini datang ke rumah?
“Bagaimana keadaanmu?” tanya Kouji, yang membuatku kembali tersadar dari lamunanku. Namun, aku mendiamkannya. Aku tidak ingin melangkah lebih dari ini. Aku sudah tidak ingin lagi bertemu dengannya meski hanya sekali saja! “Kenapa?” Kouji kembali bertanya setelah ia tidak mendengar suara apa pun dari balik pintu. “Aku tidak melihatmu di stasiun. Kau tidak ingin bernyanyi lagi?” ia melanjutkan.
“Aku sudah bosan,” jawabku memberikan alasan.
“Bohong. Nyanyianmu bagus, kok,” balas Kouji. “Kalau kamu tidak bernyanyi sekarang, mungkin kamu tidak bisa bernyanyi lagi. Aku ingin mendengarmu bernyanyi sekali saja.”
Hentikan! Berhentilah memuji nyanyianku, Kouji! Sejak pulang dari rumah sakit kemarin; sejak pembicaraanku dengan Otousan di dalam mobil itu, aku telah memutuskan untuk berhenti bernyanyi. Buat apa? Bukankah itu adalah suatu hal yang sia-sia? Aku salah kalau dulu pernah bermimpi merilis lagu ciptaanku dalam bentuk album. Kini, aku sadar kalau aku adalah Amane Kaoru, cewek berumur enam belas tahun penderita XP yang menulis lagu hanya sekadar untuk mengisi malam-malamnya yang sepi. Dan pujian-pujianmu barusan, Kouji, mengingatkanku kalau aku jelas-jelas tidak mungkin mewujudkan mimpiku!
Aku telah membuang keinginanku. Impianku. Masa depanku.
“Aku...,” ujarku tertahan kepada Kouji, “kuharap aku dapat hidup sepeti cewek biasa.” Ya, cewek biasa. Hidup seperti ratusan cewek normal lain yang memiliki cita-cita sama denganku untuk menjadi penyanyi, hanya saja mereka memiliki peluang jauh lebih besar untuk mewujudkannya. Hidup sebagaimana cewek biasa yang dapat menyukai seseorang tanpa harus dihantui sejenis penyakit mematikan. “Hanya itu yang kuinginkan.” lamjutku.
Kouji terdiam. Ia tidak membalas kata-kataku.
“Jangan ke sini lagi,” lanjutku tegas. “Kalau kamu terlibat lebih jauh denganku, tidak akan ada gunanya,” ujarku sambil berbalik. Setelah itu, aku berlari ke atas menuju kamarku dengan masih meninggalkan Kouji berdiri di luar sana. Meskipun hatiku terasa sakit, tapi aku harus melakukan ini! Kalau tidak, aku hanya akan menaruh harapan palsu kepada cowok itu, sama seperti saat Otousan mengatakan aku akan tumbuh seperti gadis normal bertahun-tahum silam.
bersambung ke bab 6
Tag :// Articles,
Tag :// YUI