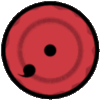Posted by : Dewi Otaku
Sabtu, 21 Januari 2012
Bab 7
Hari Esok Tiada yang Tahu
Kejadian pada malam itu telah membuatku menjadi semakin dekat dengan Kouji. Ia sendiri selalu datang ke rumahku setiap malam sesuai janjinya. Kalau ia sudah datang, kami biasanya akan melakukan banyak hal menyenangkan bersama. Pernah suatu ketika ia berkata ingin mencoba memainkan gitarku. Aku sendiri sebenarnya tidak yakin kalau Kouji bisa memainkan gitar, tapi meskipun begitu, aku tetap menyerahkan gitarku. Benar saja, begitu ia mulai bemain, terdengar bunyi fals yang membuatku ingin menutup kuping. Kami berdua lantas tertawa bersama sesudahnya.
Aku memang menikmati malam-malamku bersama Kouji, tapi aku juga harus ingat kalau ada tawaran rekaman yang masih harus kukejar. Itulah sebabnya aku sekarang hampir tak pernah keluar setelah makan malam dan lebih banyak mengurung diri di kamar untuk berlatih. Seperti malam ini. Aku kembali memegang gitarku dan bersiap untuk memainkannya sementara Misaki—yang mampir kemari untuk menginap—tidur-tiduran di kasurku sambil membaca sesuatu. Sepupuku itu masih libur musim panas, ingat?
Begitu aku mulai menggenjreng gitarku, alunan akustik yang merdu dan suara dengunganku mulai terdengar memenuhi kamar. Sengaja kupilih bagian terakhir laguku karena pada bagian itulah yang belum begitu kukuasai. Aku terus memainkan bagian itu sambil menikmati suaranya ketika tiba-tiba saja jari tangan kiriku yang kugunakan untuk membentuk akord gitar melemah dan terlepas dari senar, membuat permainanku menjadi terhenti sejenak. Kuulangi genjrenganku sekali lagi, dan untuk yang kedua kalinya, jariku terlepas lagi. Entahlah, sepertinya ada sesuatu yang salah. Jari-jariku terasa kaku dan tak bisa kugerakkan sesuai keinginanku. Aku memandangi jari-jari itu sejenak sebelum akhirnya terkaget karena tiba-tiba saja Misaki bertanya mengapa aku berhenti.
“Sepertinya aku agak capek,” jawabku sambil beringsut dari lantai. “Aku akan mengambil makanan,” lanjutku. Aku kemudian keluar dari kamar dan lalu berjalan menuruni tangga ke arah cermin yang tergantung di ruang keluarga. Sekali lagi, aku mengamati jari-jari tangan kiriku. Jari-jari itu kukepalkan dan kulepas berulang-ulang, hingga setelah aku mantap kalau kekuatan genggamanku sama seperti biasanya, aku mengangguk dan lantas beranjak ke kulkas untuk mengambil makanan. Tak apa, Kaoru, tak ada yang salah. Kamu hanya kecapekan saja karena harus mempersiapkan rekaman pertamamu, itu saja.
Setelah mengambil sesisir pisang, dua mangkuk puding, dan dua kaleng manisan, aku kemudian kembali naik ke kamar. Misaki langsung menyambutku dengan gembira saat melihatku membawakan panganan-panganan itu, dan sesaat setelah aku meletakan kesemuanya di meja, ia dengan segera menyahut semangkuk puding. Aku sendiri lebih memilih untuk melanjutkan memainkan gitarku untuk memastikan kalau tangan kiriku baik-baik saja. Satu genjrengan. Dua genjrengan. Sebuah intro. Hei, sepertinya jari-jariku memang berfungsi seperti biasa....
PANG!
Lagi-lagi...! Untuk ketiga kalinya, jari tangan kiriku kembali tidak dapat kugerakkan. Perlahan, kuamati tangan kiriku. Benar, tangan itu terasa seperti mati rasa. Tak peduli bagaimana aku menggerakkan jari telunjuk, jempol, atau kelingkingku, tidak ada yang berubah—semuanya masih tetap diam. Namun, aku mencoba untuk tidak berputus asa, jadi aku lantas memulai untuk memainkan gitarku sekali lagi. Kuangkat tangan kananku untuk mulai memetik senar gitar, dan....
PANG!
Apa ini?
Tadi jari-jari tangan kiriku yang tak bisa kugerakkan, sekarang kenapa jari-jari tangan kananku yang jadi begini? Jemari yang biasanya lincah memainkan senar nilon itu kini tidak bisa lagi kuarahkan. Aku kembali mencoba untuk memetik gitarku sebagaimana biasanya, tapi yang terdengar justru suara petikan yang keras dan sumbang. Bagaimana mungkin? Ini bukanlah permainan gitarku. Aku tetap tidak bisa menerima kalau performance-ku menjadi berantakan begini, jadi aku menggenjreng lagi sambil berharap jariku akan lentur kembali dengan sendirinya. Namun, hasilnya tetap sama, bahkan menjadi lebih parah. Aku lalu menggenjreng sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Berulang-ulang, senar gitar itu kupetik tanpa jeda, menghasilkan suara cempreng yang berkelanjutan. Meskipun begitu, jariku tetap saja terkejur dan tidak bisa menghasilkan suara yang merdu seperti biasanya.
Apa ini?
Kenapa...kenapa aku tidak bisa menggerakkan jari-jariku?
***
Otousan langsung membawaku dan Okaasan menemui dokterku begitu aku menyampaikan keluhanku. Ia titip rumah kepada Misaki, dan tidak lama kemudian, kami sudah berada di dalam mobil yang menuju ke rumah sakit. Padahal, sekarang sudah lumayan larut, sekitar jam sembilan malam. Untunglah, dokterku kebetulan tengah ada di rumah sakit dan belum pulang. Atas saran dokterku, aku lalu setuju untuk melakukan CAT-scan, dan kira-kira satu jam kemudian, dokterku lantas memanggil kami bertiga untuk membeberkan diagnosisnya.
“Meskipun untuk saat ini tingkatnya tidak begitu parah, tapi otaknya tengah mengalami kemunduran,” kata dokterku kepada Otousan. Ia memperlihatkan hasil CAT-scan sekali lagi, kemudian melanjutkan, “Saya bisa bilang kalau gejala pelemahan syaraf yang disebabkan oleh XP sudah mulai tampak.”
Sambil berbaring di ruang praktik, aku menguping pembicaraan keduanya. Pelemahan syaraf? Apa itu berarti aku tidak bisa bermain gitar lagi? Aku menengok sejenak ke arah Okaasan, dan tanpa kuminta, ia langsung menggamit tanganku untuk membuatku sedikit lebih tenang.
“Untuk ke depannya,” kata doketerku lagi, “tubuhnya akan menjadi kaku. Kemudian...,” ia menggantung kalimatnya.
“Maksud Sensei, dia akan meninggal?”
Apa?
Apa itu benar?
Aku, sekali lagi, mengerling ke arah Okaasan. Dapat kurasakan genggaman tangannya menguat, seakan-akan ia ingin mengalirkan lebih banyak kekuatan kepadaku. Otousan sendiri dengan kasar bangkit dari kursi dan lalu berjalan meninggalkan ruangan praktik. Dokterku menyusul tak lama kemudian, dan karena aku ingin tahu apa yang terjadi, aku mengajak Okaasan untuk melihat keduanya dari kejauhan.
Otousan ternyata berhenti di lobi rumah sakit. Ia duduk di situ sendirian sementara dokterku beranjak mendekatinya. Selama beberapa saat, tidak ada percakapan di antara mereka, sampai akhirnya lamat-lamat aku mulai mendengar Otousan berbicara. “Tapi bukankah ini aneh, Sensei?” tanyanya. “Aku tidak pernah membiarkannya terkena sinar matahari.” Ia menghela nafas sejenak. “Ketika ia kecil, ia selalu merengek ingin pergi ke luar,” kata Otousan menambahkan, “dan tak peduli dia menangis atau beteriak, aku akan menamparnya dan tetap menguncinya di dalam rumah.”
Ah, ya. Aku ingat. Waktu masih kecil, aku memang seringkali hanya dapat melihat teman-teman sebayaku bermain petak umpet di musim panas. Tentu saja aku juga ingin bergabung bersama mereka, tapi Otousan selalu melarangku keluar, dan bahkan memukulku di wajah. Kala itu aku tidak tahu alasan Otousan melakukannya. Namun, semakin aku beranjak remaja, aku jadi semakin paham kenapa.
“Tapi mengapa,” tiba-tiba, Otousan kembali berbicara, “mengapa semuanya jadi begini?” Perlahan, kudengar nada bicara Otousan berubah. Dari yang tadinya hanya lamat-lamat menjadi semakin keras. “Aku melakukan semua yang kubisa untuk melindunginya,” ujar Otousan. Sekarang suara tangis mulai terdengar di antara kata-katanya. “Apa itu artinya semuanya itu sia-sia? Dan kenapa, Sensei,” ujarnya kepada dokterku, “kenapa putriku harus mengalami hal semacam ini?”
Aku mengamati saat Otousan terisak dan dokterku menenangkan dirinya. Tanpa kusadari, tiba-tiba saja air mataku pun ikut meleleh. Selama ini, seburuk apa pun kondisiku, Otousan tidak pernah menitikkan air mata di hadapanku. Ia paling-paling hanya merespons sejenak dan kemudian membawaku ke rumah sakit kalau memang dirasanya perlu.
Sekarang, ia menangis.
Rasanya, baru kali ini aku benar-benar merasakan betapa Otousan menyayangiku. Aku seringkali menganggap ia tidak pedulian terhadap diriku, dan itu sebabnya aku kadangkala tidak segan untuk menyentaknya. Namun, sekarang aku sadar kalau ternyata Otousan amat menyayangiku.
Untuk kedua kalinya, aku kembali merasakan air mata mengalir membasahi pipiku.
***
Kouji kembali berkunjung ke rumaku keesokan malamnya, seperti biasa. Namun, kali ini ia tidak datang untuk melakukan suatu hal yang konyol bersamaku seperti malam-malam sebelumnya. Ia datang untuk membesukku. Misaki sempat menelepon tadi sore dan memberi tahu Kouji mengenai keadaanku yang sekarang, jadi aku tidak perlu bercerita panjang lebar mengenai hal itu. Ah, selalu saja begitu. Selalu saja ia yang menginformasikan segala hal tentang penyakitku kepada Kouji. Sudahlah, setidaknya aku jadi tidak usah repot-repot.
Aku tengah tidur-tiduran di atas kasur ketika kudengar Kouji memanggil namaku. Cepat- cepat kuubah posisiku menjadi duduk bersadar di dinding. Masa’ aku menyambut Kouji dengan telentang? Tidak sopan!
“Aku masuk, ya,” kata Kouji. Tak lama kemudian, aku melihat sosoknya berjalan melewati pintu geser kamarku. Pintu itu memang kubiarkan terbuka supaya aku dapat mendengar Okaasan memanggil atau, jika aku butuh bantuan seseorang, maka aku dapat dengan mudah memanggilnya. Kami saling berpandangan selama beberapa saat sebelum akhirnya Kouji berkata kepadaku, “Bagaimana keadaanmu?”
Sebagai jawaban, aku terdiam. Kepalaku sedikit kuarahkan ke tangan kiriku, tanda aku masih kesulitan menggerakkkannya. Kouji sendiri sepertinya langsung paham dengan gerakanku barusan sehingga ia tidak bertanya lagi. Harus kuakui, tindakan Misaki tadi siang sedikit banyak sudah membantuku.
“Maaf, ya,” ujarku tiba-tiba.
Ekspresi Kouji langsung berubah menjadi heran setelah mendengar kata-kataku itu. “Apa?” tanyanya.
“Meskipun kamu sudah bekerja paruh-waktu...,” jawabku lirih, “pada akhirnya, aku tidak bisa menyanyi lagi.” Aku menunduk semakin dalam sementara Kouji menatapiku. “Maafkan aku.”
Alih-alih menanggapi, Kouji justru berjalan menjauh. Ia melangkahkan kakinya menuju jendela kamar yang dulu sering kugunakan untuk memperhatikannya di halte bus, lalu setelah melongok ke luar sejenak, ia bertanya padaku, “Aku tidak melakukan sesuatu yang aneh, kan?”
“Hah?”
“Kamu kan biasa melihatku dari sini,” jawab Kouji seraya menunjuk jendela itu.
Aku bangkit dari sandaranku, kemudian beringsut ke sisi tempat tidur. “Hal aneh seperti yang kamu maksud?” tanyaku.
“Misalnya aku mengupil....”
“Tidak kok,” jawabku sambil tertawa kecil. Ada-ada saja.
“Kalau suara-suara yang aneh?”
“Tidak.”
Mendengar jawabanku, Kouji terlihat lega. “Yang betul? Senang mendengarnya kalau begitu.”
Aku lantas bangkit dari kasur dan berjalan ke arah Kouji—yang sekaligus juga ke arah jendela itu. Kulongokkan kepala sejenak untuk mengintip ke luar. Gelap. Hanya cahaya lampu rumah jalanan yang bisa kulihat, atau cahaya mesin penjual otomatis di halte bus. Aku menatap halte bus itu selama beberapa saat sebelum akhirnya berpaling ke arah Kouji. “Pertama kali aku melihatmu,” aku memulai percakapan, “aku melihat Kouji yang seperti anak-anak,” lanjutku. Aku langsung menyadari kalau Kouji menatapku dengan tatapan memohon dan aku tahu kalau ia ingin aku menceritakan apa maksud dari pernyataanku barusan. Aku tersenyum kecil, setelah itu mulai bertutur.
Waktu itu, aku masih empat belas tahun—sekitar kelas 2 SMP. Sudah menjadi kebiasaanku untuk duduk-duduk di samping jendela sebelum matahari terbit (dan masih berlanjut sekarang) sambil melihat ke jalanan di depan halte bus. Pada suatu pagi, aku melihat ada seorang cowok menghentikan skuternya di dekat halte itu—Kouji. Cowok itu mengenakan rompi, kemeja putih, dan celana hitam sambil menenteng tas, jadi aku tahu kalau dia hendak berangkat sekolah. Ia lantas turun dari skuter dan lalu berjalan mendekati sebuah papan seluncur. Diamat-amatinya papan seluncur itu dan dielus-elusnya, seakan-akan ia kagum betul dengan benda itu. Tak cukup dengan itu, ia juga membaringkan papan seluncur itu di tanah. Ia kemudian berpose seakan-akan tengah berselancar di atas ombak. Ketika ia hendak menaiki papan itu, seorang pria berotot dan bertelanjang dada keluar dari sebuah toko. Pria itu lantas menegurnya karena telah bermain-main dengan papan miliknya, dan aku melihat cowok itu langsung bertubi-tubi minta maaf. Aku tertawa sendiri melihat kejadian itu.
Beberapa hari kemudian, aku kembali melihat cowok itu. Kali ini, ia tidak sendirian. Ada dua orang lain bersamanya, dan kulihat ia tengah memamerkan papan seluncur yang baru dibelinya. Aku tersenyum melihat ketiganya bercanda, lebih-lebih ketika ia lantas memelorotkan celana sehingga celana pendeknya terlihat. Waktu itu aku sadikit terkejut juga. Namun, keterkejutanku berubah menjadi sebuah tawa saat melihatnya terjatuh karena tersandung celananya sendiri.
“Pada waktu itu kamu terlihat bahagia,” aku mengakhiri ceritaku sambil sekali lagi memandang ke arah halte bus di bawah. “Melihatmu seperti itu, aku juga turut bahagia.”
“Ah, kamu melihatnya,” kata Kouji seraya tersenyum malu.
“Aku juga seperti itu, kok.”
“Heh?”
“Waktu pertama kali mendapat gitar,” terangku, “aku juga gembira seperti kamu.”
“Begitu, yah...,” gumam Kouji perlahan.
Setelah itu, intensitas percakapan kami langsung berkurang drastis. Kouji lebih banyak diam, dan begitu pula aku. Yang kami bicarakan paling-paling hanya hal-hal tak penting seperti bagaimana Kouji menghabiskan liburannya atau apakah aku sudah membuat lagu baru lagi akhir-akhir ini. Namun, kami sama sekali tidak membicarakan keadaanku. Tidak sedetik pun.
Setelah Kouji menghabiskan waktu bersamaku dengan kekakuan yang amat terasa, ia lantas beranjak untuk pamit. Aku mengantarkan Kouji keluar rumah dan bahkan ketika ia mulai menuruni tangga beranda rumahku, aku masih memandanginya. Ia sempat menoleh ke arahku sejenak ketika hendak berlalu, sedangkan aku hanya membalas dengan senyuman kecil.
“Hei!” seruku ketika Kouji sudah hampir berada di bawah. “Meskipun tanganku seperti ini, kamu bisa mendengar suaraku, kan?”
Kouji terdiam. Ia menatap ke arahku selama beberapa saat tanpa suara.
“Kamu bisa mendengarnya, kan?” aku mengulangi pertanyaanku.
“Ya, aku bisa mendengarnya,” balas Kouji dari bawah sana.
Aku tersenyum sejenak mendengar jawaban Kouji. “Kalau begitu, aku akan bernyanyi,” aku melanjutkan. Benar. Meskipun aku tidak dapat bermain gitar lagi, tapi setidaknya aku masih dapat menggunakan suaraku untuk bernyanyi, kan? Itu berarti aku masih mungkin pergi ke perusahaan rekaman dan membuat CD debutku. Setidaknya, usaha Kouji bekerja paruh-waktu tidak akan sia-sia. “Sampai besok kalau begitu!” seruku sembari melambaikan tangan kepada Kouji.Aku kemudian berlari naik menuju rumah. Sebelum masuk, aku sempat melihat ke bawah, ke arah Kouji yang kini tengah berjalan menjauh. Di antara lampu jalanan, sepintas aku melihat bahu Kouji naik turun. Kouji...masa’ sih dia menangis?
bersambung ke bab 8
***